Laman: 1 2
Buku IV-27
The URI to TrackBack this entry is: https://adbmcadangan.wordpress.com/buku-iv-27/trackback/
The URI to TrackBack this entry is: https://adbmcadangan.wordpress.com/buku-iv-27/trackback/

Gambar Kulit :
Herry Wibowo
Ilustrasi :
Sudyono
Penerbit :
Kedaulatan Rakyat,
Yogyakarta
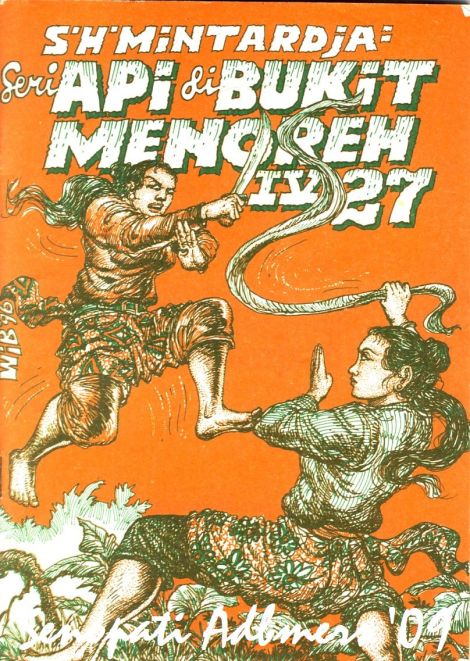
matur nuwun… Nyi Seno. ransume munjung…
3x Matur Nuwun Nyi
thxs…bgt..
top dech.. 🙂
Sekedar Guyonan Ni
Top apa yang bisa bikin Adem kepala ???
Yang pasti bukan TOPI Ni……………
monggo,
apa ya ki???
topan mandi dikali???
heheheheh..
nyerah dech..
matur suwun ki/nyai kitab sampun diunduh
Matur suwun Nyi Senopati.
Kitab sampun diunduh.
Matur nuwun sampun ngunduh, buah dari kesabaran
Terima kasih… Nyi & Q GD
nyi Seno yth, el kitap sampun di undhuh. Mohon nyi Seno berkenan memberitahu kami untuk bantu menumpas gerombolan pengacau di bumi mataram.
Huasyik tenan ……. Trims Nyi Seno lan Ki GD …
Muantep tenan Nyi.
3 hari tidak masuk kerja (libur sabtu, minggu, senin) njenguk adbm senin sore ada tiga kitab di wedar muantep tho, enaak tho, hi hi hi I Love You Full
Salam ADBM untuk semua
rapelan terima kasih juga untuk nyi sena, ki gd, ki sukra, ki mbodo, ki tumenggung sepuh serta para bebahu dan para pengawal padepokan…
ternyata di sini semua to? 😀
Dear all
nyuwun tulung, shabis don lot trus untuk bukanya diapain ya mas,,,
nyuwun tulung
suwun
kant
coba buka link ini Ki.
Klik untuk mengakses donlot-kitab-wakita.pdf
Biasanya Ki Sunda sekali upload dua jilid, makanya gandok ini saya bersihkan sekalian.
Monggo Ki Sunda…. 😀
Hadir aaahhh ….
saba padepokan ah..tamba kangen
Api di Bukit Menoreh
Jilid IV – 27
Bagian 1 dari 3
TETAPI Pandan Wangi tidak memburunya. Dibiarkannya perempuan itu mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya
“Kau memang sombong perempuan cantik,” geram perempuan itu, “kau beri kesempatan aku bersiap menghadapi seranganmu. Kau sengaja memberi waktu kepadaku. Tetapi kau akan menyesal. Waktu yang sekejap, yang kau berikan kepadaku ini akan mengubah segala-galanya.”
“Aku tahu, kau bukan perempuan yang bengis. Kau hanya kurang bertenggang rasa dengan orang lain, sehingga kau dan kawan-kawanmu merasa diri kalianlah yang terpenting di dalam pergaulan ini. Karena itu, aku juga tidak ingin bertindak kasar.”
“Kau salah duga, perempuan cantik,” berkata orang itu, “kami bukan orang baik-baik. Kami dapat berbuat jauh lebih jahat dari penjahat yang manapun juga.”
“Ternyata kalianlah yang baru turun dari sebuah perguruan,” berkata Pandan Wangi kemudian, “bukan kami. Karena itu, pengalaman ini perlu bagi kalian. Tetapi pada dasarnya kalian bukan orang-orang jahat. Ancaman kalian pun masih sebatas ancaman yang sepatutnya.”
Tetapi lawan Pandan Wangi itu menyahut, “Kau jangan merajuk perempuan cantik. Kau jangan mengira, bahwa pujianmu itu akan meluluhkan hatiku sehingga aku tidak berbuat jahat terhadapmu.”
“Seandainya kau akan berbuat jahat, apa yang akan kau lakukan terhadapku?”
“Menyakiti kau dan suamimu sampai kalian menjadi jera. Jika kita bertemu lagi, maka kau tidak akan berani menengadahkan wajahmu. Apalagi jika kau mendengar kami membentakmu, maka kau akan segera bersimpuh di bawah telapak kakiku.”
“Hanya itu?”
“Jadi apa lagi?”
Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba ia pun bertanya, “Kalian pedagang hewan?”
“Ya.”
“Dagangan kalian telah laku semuanya?”
“Ya.”
“Bagus!”
“Apa yang bagus?” bertanya perempuan itu.
“Tidak apa-apa. Tetapi apakah kita akan bertempur terus.”
“Kau takut?”
“Tidak. Aku berjanji jika kau menang, aku akan menjadi jera mencampuri urusanmu. Tetapi jika sebaliknya kau yang kalah, maka kau pun harus menjadi jera. Kau akan berlaku baik di tempat banyak orang. Kau dan kawan-kawanmu akan menghargai orang lain dan tidak akan menyakiti hati mereka.”
Perempuan itu mengerutkan dahinya. Katanya, “Baik. Aku berjanji.”
Demikianlah, maka keduanya pun segera bersiap. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah bertempur lagi dengan sengitnya Keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka sampai ke puncak.
Namun ternyata bahwa kemampuan Pandan Wangi masih lebih tinggi dari kemampuan lawannya. Karena itu, maka semakin lama justru Pandan Wangilah yang semakin mendesak. Serangan-serangannya semakin lama menjadi semakin sering mengenai tubuh lawannya. Meskipun sekali-sekali serangan lawannya juga mengenainya, tetapi serangan-serangan itu tidak mematahkan penahanan Pandan Wangi.
Bahkan serangan kaki Pandan Wangi yang mengenai lambung perempuan itu, telah melemparkannya. Tubuhnya terpelanting jatuh menimpa bebatur kedai, sehingga perempuan itu mengaduh kesakitan.
Tetapi perempuan itu pun segera bangkit. Meskipun mulutnya menyeringai, namun kemudian tiba-tiba saja tangannya telah mengurai selendang yang melingkar di perutnya.
Pandan Wangi bergeser mengambil jarak. Sementara perempuan itu memutar selendangnya.
“Aku terpaksa mempergunakan senjataku, perempuan cantik. Jangan menyesali nasibmu. Jika terjadi sesuatu yang paling buruk atas dirimu, itu bukan maksudku. Tetapi aku tidak dapat membiarkan harga diriku kau injak-injak.”
Pandan Wangi termangu-mangu sejenak. Ia sudah sering mendengar dan bahkan mengalami benturan ilmu dengan perguruan yang mempergunakan benda-benda lentur sebagai senjatanya. Tetapi jika tenaga dalam orang itu cukup tinggi, maka selendang itu akan dapat menjadi sangat berbahaya. Selendang itu dapat terjulur seperti sekeping logam yang tajam. Dapat pula menebas seperti pedang. Tetapi dapat menjerat seperti janget kenatelon.
Sementara itu perempuan itu masih berkata selanjutnya, “Tetapi aku tidak akan ingkar janji. Jika kau kalah, kau akan menjadi jera dan minta ampun kepada kami semuanya. Tetapi sebaliknya, jika aku kalah, maka aku akan memperbaiki tingkah laku. Bukan hanya tingkah lakuku, tetapi kelompokku ini.”
Pandan Wangi mengangguk. Namun ia menyempatkan diri untuk melihat, apa yang terjadi dengan Swandaru.
Nampaknya Swandaru memang tidak terlalu bernafsu ingin cepat mengalahkan lawannya. Justru Swandarulah yang ingin tahu, unsur-unsur gerak ilmu lawannya. Jika saja ia dapat mengenalinya maka ia akan dapat menelusuri perguruan dari kedua orang perempuan itu.
Tetapi ketika lawan Swandaru itu melihat lawan Pandan Wangi sudah mengurai selendangnya maka ia pun segera mengurai selendangnya pula.
Swandaru juga bergeser surut mengambil jarak. Ternyata Swandaru tidak lagi merasa tegang menghadapi lawannya justru setelah ia sempat menjajaki ilmunya. Meskipun keduanya bertempur dengan sengitnya, namun Swandaru sudah mampu menilai tataran kemampuan perempuan itu.
Namun ketika lawannya mengurai selendangnya maka Swandaru pun berdesis, “Kau membuat dirimu semakin sulit.”
“Kau menjadi ketakutan, Ki Sanak. Selendang ini akan segera dapat mengakhiri perlawananmu.”
“Atau justru sebaliknya. Karena kau bersenjata, maka aku pun akan mempergunakan senjata. Kita masing-masing tahu, akibat dari orang-orang yang bermain-main dengan senjata.”
“Apa boleh buat. Sejak kita mengenal senjata, kita sudah tahu, bahwa senjata itu akan dapat menyakiti kita dan bahkan lebih dari itu. Mungkin senjata itu akan dapat mengakhiri petualangan kita untuk selanjutnya, meskipun tidak dengan sengaja.”
Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Baiklah, kau mendesakku. Aku tidak dapat berbuat lain. Tentu saja aku tidak akan membiarkan diriku menjadi cedera oleh senjatamu.”
Perempuan itu tidak menjawab. Tetapi ia pun segera memutar selendangnya.
Swandaru merasakan desir angin oleh putaran selendang itu. Ketika lawannya menggerakkan selendangnya mendatar, maka Swandaru pun menyadari, bahwa tenaga dalam perempuan itu cukup besar.
Dengan demikian, maka Swandaru tidak boleh lengah. Jika selendang itu sempat menyentuh kulitnya, maka kulitnya itu tentu akan terluka.
Sementara itu, lawan Pandan Wangi pun telah mulai mengayunkan selendangnya. Pandan Wangi dengan cepatnya meloncat mengambil jarak. Ketika selendang itu dihentakkan sendal pancing, maka sekali lagi Pandan Wangi harus meloncat dengan cepat ke samping.
Selendang itu tidak mengenainya. Tetapi getar angin yang tersentuh ayunan selendang itu telah menerpa tubuh Pandan Wangi sehingga keseimbangannya menjadi goyah.
“Luar biasa!” desis Pandan Wangi.
Ia sadar sepenuhnya, maka lawannya benar-benar menguasai senjatanya serta memiliki tenaga dalam yang cukup memadai.
Karena itu, maka Pandan Wangi tidak dapat melawannya dengan kedua tangannya saja. Ketika ia harus melenting mengambil jarak, maka tiba-tiba saja kedua tangannya telah menggenggam sepasang pedangnya.
Jantung lawannya tersirap. Demikian pedang itu berada di tangan Pandan Wangi, maka pedang itu pun langsung berputar, sehingga merupakan perisai pertahanan yang sangat rapat
“Bukan main!” desis perempuan itu.
Namun yang lebih terkejut lagi adalah perempuan yang seorang lagi. Bahkan ketujuh orang laki-laki yang berdiri di sekitar arena itu, Di tangan Swandaru tiba-tiba pula telah digenggam tangkai cambuknya yang berjuntai panjang.
Swandaru pun menghentakkan cambuknya itu sehingga terdengar cambuk itu meledak bagaikan meruntuhkan langit.
Orang-orang yang mendengar ledakkan cambuk Swandaru itu menutup telinganya. Rasa-rasanya selaput telinga mereka akan terkoyak oleh ledakan yang sangat keras itu.
Namun perempuan yang bertempur melawan Swandaru itu berdiri termangu-mangu sambil berkata, “Apakah kau murid dari perguruan Orang Bercambuk?”
“Ya,” jawab Swandaru.
“Sayang, bahwa kau berguru setelah orang bercambuk yang sebenarnya tidak ada, sehingga ilmumu lebih sesuai kau pergunakan untuk menggembalakan kambing daripada untuk membela diri dalam benturan ilmu yang sebenarnya.”
Swandaru tersenyum. Justru karena keyakinannya akan kelebihannya, maka Swandaru tidak merasa tersinggung. Tanpa menjawab sama sekali, maka sekali lagi Swandaru menghentakkan cambuknya
Berbeda dengan hentakkan sebelumnya, maka hentakkan cambuknya itu sama sekali tidak meledak. Bahkan seakan-akan tidak bersuara sama sekali.
Namun perempuan yang bersenjata selendang itu telah terkejut pula. Hentakkan ilmu cambuk yang matang itu benar-benar telah menggetarkan jantung perempuan itu.
“Luar biasa!” perempuan itu berdesis di luar sadarnya.
“Apakah pertempuran ini akan kita lanjutkan?” bertanya Swandaru.
Perempuan itu termangu-mangu. Namun ternyata harga dirinya cukup tinggi. Karena itu, maka katanya, “Pantaskah jika aku berjongkok untuk menyerahkan diriku kepadamu?”
“Soalnya bukan pantas atau tidak pantas. Tetap kau tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa kau tidak akan mampu melawan ilmu cambukku.”
Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, “Siapakah yang lebih dahulu menang. Kau atau saudaraku yang bertempur melawan istrimu. Jika kau lebih dahulu menang, maka kau dapat membantu istrimu mengalahkan saudaraku. Tetapi jika saudaraku itu menang, maka ia akan dapat membantuku, menghentikan perlawananmu.”
“Bagaimana kalau istriku menang atas saudaramu itu?”
“Apakah istrimu juga berilmu sangat tinggi?”
“Kita akan melihat. Tapi seandainya tidak, maka aku akan berusaha mengalahkanmu lebih dahulu.”
Perempuan itu tidak menjawab. Namun ia pun kembali memutar selendangnya Putaran angin mulai menghentak-hentak di arena Bahkan ayunan selendang itu mendatar, menjadi sangat berbahaya pula bagi Swandaru.
Tetapi Swandaru pun telah memutar cambuknya pula. Sekali ia menghentakkan cambuk itu sehingga meledak bagaikan memecahkan selaput telinga, namun kemudian cambuk itu menghentak tanpa bersuara sama sekali. Tetapi getarannya mengguncang isi dada.
Sementara itu, Pandan Wangi pun telah melindungi tubuhnya dengan sepasang pedang rangkapnya. Putaran pedangnya bagaikan kabut putih yang membentengi dirinya tanpa memberikan kesempatan ujung duri untuk menyusupinya.
Lawan Pandan Wangi itu pun kemudian telah menghentakkan senjatanya dengan mengerahkan tenaga dalamnya.
Yang kemudian terjadi adalah satu benturan yang keras. Selendang lawan Pandan Wangi itu tidak menyentuh putaran pedangnya dengan lunak. Tetapi yang terjadi adalah benturan tenaga dalam kedua orang perempuan yang sedang bertempur itu.
Perempuan itu terkejut. Ia terdorong berapa langkah surut, selendangnya yang membentur pedang Pandan Wangi dengan keras itu tergetar. Getarannya seakan-akan telah merambat lewat selendang itu, menelusuri tangannya dan mengguncang isi dadanya. Meskipun perempuan itu telah mengerahkan tenaga dalamnya pula, namun ternyata tenaga Pandan Wangi masih lebih besar dari tenaga dalamnya, sehingga dalam benturan yang terjadi tenaga dalam Pandan Wangi telah mendesak dan bahkan menghentak jantung.
Perempuan itu meloncat surut untuk mengambil jarak. Sambil berdiri tegak, maka kedua tangan perempuan itu memegangi kedua ujung selendangnya. Sementara terasa jantungnya berdebar-debar di dalam dadanya.
Pandan Wangi tidak mengejarnya Selangkah ia maju sambil berkata, “Kita sudah dapat menduga, apakah yang akan terjadi.”
“Tidak!” jawab perempuan itu, “Pertempuran tidak ditentukan hanya oleh kekuatan tenaga. Bahkan tenaga dalam sekali pun. Tetapi ada unsur lain yang ikut menentukan, apakah kau atau aku yang akan menang.”
“Kau benar,” jawab Pandan Wangi, “jadi kita akan meneruskan sampai kita yakin, siapakah di antara kita yang menang dan yang kalah?”
“Ya.”
“Tetapi sorot matamu berkata lain,” desis Pandan Wangi, “matamu memancarkan pengakuan atas kekuranganmu.”
“Kau menjadi semakin sombong.”
“Bukan maksudku. Aku hanya ingin meyakinkanmu, bahwa bijaksana sekali menyelesaikan pertempuran pada saat seperti ini.”
Orang itu mengerutkan dahinya Tiba-tiba saja berteriak, “Bersiaplah!”
Sejenak kemudian, maka perempuan itu pun telah menyerang Pandan Wangi. Selendangnya menghentak sendal pancing.
Tetapi Pandan Wangi sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, maka dengan cepat pula ia menghindar. Bahkan dengan cepat pula ia meloncat sambil menjulurkan pedang di tangan kirinya.
Tetapi perempuan itu telah menyongsong serangan itu dengan menjulurkan selendangnya mematuk ke arah dada.
Pandan wangi menggeliat. Dengan pedang di tangan kanannya ia menangkis selendang lawannya yang terjulur ke dadanya.
Namun selendang itu dengan lunak menyentuh pedang Pandan Wangi. Bahkan kemudian telah melilit dan seakan-akan dengan kerasnya mencengkam pedang itu.
Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, maka perempuan itu dengan cepat menarik selendangnya yang melilit pedang itu. Dengan kuatnya pedang Pandan Wangi seakan-akan telah dihisap oleh kekuatan tenaga dalam perempuan itu.
Tetapi Pandan Wangi ternyata telah memperhitungkannya. Karena itu, ketika perempuan itu menghentakkan selendangnya untuk merampas pedang Pandan Wangi, maka selendangnya seakan-akan telah melilit sebatang pohon yang akarnya menghunjam sampai di pusat bumi.
Karena itu, hentakkan tenaganya tidak berhasil menarik pedang Pandan Wangi. Justru perempuan itu sendirilah yang seakan-akan telah terhisap oleh kekuatan yang merambat dari pedang Pandan Wangi itu.
Untunglah bahwa perempuan itu cepat tanggap akan kesulitan yang bakal dihadapi. Jika ia tidak dapat bertahan, maka pedang di tangan kiri Pandan Wangi itu akan dapat terjulur menyongsong tubuhnya yang meluncur ke arah pedang yang dililit oleh selendangnya.
Dengan demikian, maka dengan cepat, maka perempuan itu telah mengurai selendangnya sehingga pedang Pandan Wangi itu terlepas. Namun dengan demikian, maka tubuhnya tidak lagi terhisap tanpa dapat bertahan.
Pandan Wangi termangu-mangu sejenak. Jika ia berminat melakukannya, maka dengan satu loncatan, maka pedang di tangan kirinya itu akan dapat menggapainya, justru pada saat perempuan itu dalam kesulitan. Tetapi Pandan Wangi tidak melakukannya. Ia bahkan berdiri tegak sambil tersenyum memandangi perempuan yang terlepas dari hisapan daya tariknya sendiri.
“Kenapa kau hanya diam saja?” bertanya perempuan itu.
“Apa yang harus aku lakukan?”
“Meloncat, dan menjulurkan pedang di tangan kirimu. Ujung pedang itu akan menikam dadaku, karena itu tidak akan dapat menangkis dan tidak akan sempat mengelak.”
“Lalu kau mati?”
Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Dengan kerut di dahi ia pun berkata, “Ya.”
Pandan Wangi menggeleng. Katanya, “Jika kau mati, maka kau tidak akan dapat lagi mengakui kemenanganku.”
“Cukup!” perempuan itu menjerit, “Demikian sombongnya kau, perempuan cantik. Kau rendahkan aku sampai wajahku tersuruk ke dalam tanah.”
Pandan Wangi justru tertegun melihat sikap perempuan itu. Apalagi ketika perempuan itu kemudian menjatuhkan diri dan duduk di tanah sambil menangis. Katanya dengan suara yang melengking-lengking, “Bunuh aku! Bunuh aku! Jangan hinakan aku seperti itu!”
“Tidak,” berkata Pandan Wangi, “aku tidak ingin menghinamu. Tetapi jangan paksa aku membunuhmu.”
“Di hadapanmu aku tidak berharga sama sekali. Kenapa kau tidak membunuh aku saja?”
“Kenapa aku harus membunuh?”
“Kita sudah bertempur. Kita masing-masing dapat membunuh lawan-lawan kita.”
“Tetapi kita tidak berjanji untuk saling membunuh.”
Perempuan itu pun kemudian meletakkan selendangnya di pangkuannya Sambil menangis ditutupnya wajahnya dengan kedua telapak tangannya.
Pandan Wangi justru menjadi bingung. Ia memang tidak menjadi lengah, karena dapat saja perempuan itu berpura-pura, namun kemudian dengan tiba-tiba menyerangnya. Tetapi ia pun melihat ketujuh orang laki-laki yang datang bersama kedua perempuan itu juga menjadi bingung.
Sementara itu Swandaru, yang bertempur dengan perempuan yang seorang lagi, bertanya kepada lawannya, “Kau lihat, bahwa kawanmu menyerah?”
“Ya.”
“Bahkan menangis?”
“Ya. Ia orang yang cengeng.”
“Dan kau sendiri?”
Perempuan itu tidak dapat mengingkari kenyataan. Ilmu cambuk lawannya itu tidak akan dapat diimbanginya. Ketika ujung cambuk Swandaru itu sedikit saja menyentuh lengannya, maka lengannya seakan-akan telah terkoyak dan berdarah.
“Aku menyerah,” berkata perempuan itu, “jika kau akan membunuh aku, bunuhlah.”
Swandaru termangu-mangu. Suara perempuan itu tetap datar. Tidak ada gejolak perasaan sama sekali yang menyatakan kecemasan dan kengerian menghadapi kematian seandainya kematian itu benar-benar akan datang.
“Perempuan itu tahu, bahwa aku tidak akan membunuhnya,” berkata Swandaru di dalam hatinya, “sebagaimana Pandan Wangi juga tidak membunuh lawannya. Karena itu ia tidak perlu merasa cemas.”
Namun sikapnya yang tetap tenang memang menarik bagi Swandaru, meskipun seandainya perempuan itu tahu, bahwa ia tidak akan membunuhnya.
Karena Swandaru tidak segera menanggapi sikapnya, maka perempuan itu pun mengulangi lagi pernyataannya, “Aku menyerah. Apakah kau akan membunuhku, atau aku akan kau perkenankan melihat saudaraku sebelum kau membunuhku?”
“Lihat saudaramu itu,” berkata Swandaru kemudian. Perempuan itu melilitkan selendangnya di pinggangnya. Kemudian ia pun melangkah mendekati kawannya yang masih menangis.
“Kau menangis lagi,” berkata perempuan itu.
Perempuan yang menangis itu menyahut di sela-sela tangisnya, “’Perempuan cantik itu menghinaku. Ia tidak mau membunuhku, agar aku dapat melihat dan mengakui kemenangannya.”
“Kenapa kau harus menangis?”
“Aku tidak mau dihina.”
“Akui saja, bahwa kau kalah. Aku juga menyerah dan mengaku kalah. Aku juga sudah siap untuk mati atau diperlakukan apa saja, tetapi aku tidak menangis.”
Perempuan yang menangis itu mengangkat wajahnya, Dengan selendangnya ia mengusap air matanya
“Senjatamu itu akan kehilangan arti jika terlalu sering basah oleh air mata.”
Perempuan yang menangis itu pun bangkit berdiri. Sementara perempuan yang tidak menangis itu berkata, “Kami menyerah. Kami siap untuk diperlakukan apa saja.”
Swandaru mengerutkan dahinya. Dengan suara yang berat ia bertanya, “Siapakah kalian sebenarnya?”
“Kami memang baru saja menjual beberapa ekor lembu hasil peternakan padepokan kami.”
“Padepokan mana?”
“Padepokan Trembayun di kaki Gunung Merapi.”
“Siapa nama kalian dan siapa nama pemimpin padepokan kalian yang barangkali juga merupakan sebuah perguruan?”
“Ya. Padepokan kami adalah sebuah perguruan. Namaku Onengan. Saudaraku ini namanya Praniti.”
“Siapakah pemimpin perguruanmu?”
“Guru kami adalah Ki Reksapada. Seorang yang sudah separuh baya.”
“Apa kata gurumu jika ia melihat kau dan tujuh laki-laki itu kami kalahkan?”
“Tujuh laki-laki dungu itu adalah para cantrik di perguruan kami. Aku tidak dapat mengatakan, bagaimana sikap guru, jika guru melihat kami dikalahkan. Jika kalian membunuh kami sehingga kami tidak pulang, mungkin guru akan mencari kami.”
Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, “Baiklah. Meskipun aku tidak membunuhmu, jika gurumu mencariku, biarlah ia menemui aku. Ia dapat datang ke rumahku.”
“Siapakah sebenarnya kalian berdua?”
“Namaku Swandaru. Jika gurumu ingin menemui aku, biarlah ia mencari aku di Sangkal Putung. Aku adalah anak Demang Sangkal Putung.”
“Anak Demang Sangkal Putung?” perempuan itu mengulang.
“Ya. Aku tidak keberatan menerima gurumu untuk keperluan apa saja. Tetapi aku bukan jenis orang yang mencari lawan.”
Perempuan itu mengangguk-angguk.
Sementara itu Pandan Wangi pun berkata kepada lawannya yang dikalahkannya, “Bukankah perjanjian kita tetap berlaku?”
Perempuan itu memandang Pandan Wangi dengan kerut di dahi, sementara perempuan yang lain bertanya, “Perjanjian apakah yang kalian buat?”
“Saudaramu ini berjanji jika ia kalah, maka ia dan saudara-saudaranya yang lain akan berubah sikap. Ia dan saudara-saudaranya tidak akan lagi berbuat seenaknya sendiri di antara banyak orang. Tanpa menghiraukan apakah orang lain tersinggung atau tidak. Apakah tingkah lakunya itu pantas atau tidak. Pokoknya, saudaramu berjanji untuk membuat saudara-saudaranya bertenggang rasa di dalam lingkungan orang banyak.”
Perempuan yang bertempur melawan Swandaru itu menundukkan kepalanya. Katanya, “Aku mengerti. Aku menjadi saksi perjanjian ini. Aku pun akan menghormati perjanjian itu.”
“Terima kasih.”
“Kami sadari, bahwa tingkah laku kami telah menyurukkan kami ke dalam kehinaan ini.”
“Jangan salah paham. Kami tidak bermaksud menghinakan kalian. Kami hanya tersinggung oleh sikap kalian. Itu saja.”
Perempuan itu mengangguk. Katanya, “Kami minta maaf.”
“Nah, sekarang pergilah. Kami juga akan melanjutkan perjalanan kami.”
“Kalian akan pergi ke mana?” bertanya perempuan itu.
“Kami akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Kalian akan pulang ke padepokan kalian?”
Perempuan itu hanya mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi.
Swandaru dan Pandan Wangi kemudian telah minta diri. Mereka pun minta diri pula kepada pemilik kedai yang berdiri dengan tegangnya menyaksikan perkelahian itu.
Namun sebelum Swandaru dan Pandan Wangi pergi, kedua orang perempuan itu pun berkata kepada pemilik kedai itu, “Kami minta maaf. Kami akan mengganti kerusakan yang terjadi di dalam kedai ini. Kami mempunyai uang, karena kami baru saja menjual beberapa ekor lembu dari peternakan kami.”
“Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada kerusakan yang berat. Biarlah aku memperbaikinya sendiri.”
Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berkata kepada Swandaru dan Pandan Wangi yang telah menuntun kudanya, “Singgahlah di padepokan kami. Kami akan memperkenalkan kalian berdua kepada guruku.”
“Terima kasih,” jawab Swandaru, “tetapi aku tidak tahu, apakah aku dapat memenuhi undanganmu atau tidak.”
Demikianlah, Swandaru dan Pandan Wangi pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Tanah Perdikan Menoreh.
“Perjalanan kita memang tertunda,” berkata Swandaru, “tetapi kita dapat memberi peringatan kepada orang-orang itu agar tidak membuat orang lain tersinggung.”
Pandan Wangi tersenyum. Katanya, “Tetapi nampaknya mereka bukan orang-orang jahat.”
“Apakah kita akan singgah kelak jika kita kembali dari tanah perdikan?”
Pandan Wangi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, “Meskipun kita menduga bahwa mereka bukan orang-orang jahat, tetapi apakah kita pantas terlalu mempercayai mereka? Kita tidak tahu, apakah isi padepokan mereka. Mungkin ada orang-orang yang tidak jahat, tetapi tidak mengenal unggah-ungguh seperti orang-orang yang baru saja menjual ternak itu. Tetapi mungkin di antara mereka terdapat orang-orang lain yang ternyata jahat dan pendendam.”
Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Kau benar. Jika aku berniat singgah, aku hanya ingin menjajaki kemungkinan, apakah perguruan Ki Reksapada di Trembayun itu akan dapat menjadi kawan bermain.”
“Maksud Kakang?”
“Jika Mataram tidak berniat memenuhi permohonan kami, bukankah kami perlu memberikan tekanan, sehingga Mataram mengiakannya?”
“Kakang?”
Tetapi Swandaru tertawa. Katanya, “Sudahlah. Jangan dipikirkan. itu adalah kemungkinan terakhir. Tekanan yang aku maksud itu pun hanya sekedar pameran kekuatan. Tetapi sudah tentu tidak benar-benar dipergunakan.”
“Jika tekanan itu tetap tidak dihiraukan oleh Mataram?”
“Jangan berpikir begitu. Bukankah kita sudah memberikan sumbangan banyak sekali terhadap Mataram, dan bahkan melampaui Tanah Perdikan Menoreh?”
Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Namun kecemasan telah menggelitik jantungnya. Meskipun tidak terbuka namun agaknya Swandaru ingin memaksakan keinginannya, agar Sangkal Putung dapat menjadi sebuah tanah perdikan sebagaimana Menoreh, dengan hak-haknya yang lebih besar dari sebuah kademangan.
Tetapi Pandan Wangi tidak bertanya lebih jauh lagi. Dipandanginya jalan panjang yang berbentang di hadapannya
Untuk beberapa saat lamanya mereka saling berdiam diri. Namun Swandarulah yang kemudian berkata, “Jalan menuju ke Kota Raja nampaknya menjadi sepi.”
Pandan Wangi mengerutkan dahinya. Katanya kemudian, “Panasnya terasa bagaikan menyengat kulit. Saat-saat seperti ini jalan memang menjadi agak sepi.”
Swandaru mengangguk-angguk.
Kuda mereka pun kemudian berpacu semakin cepat.
Beberapa saat kemudian mereka telah berada di tepian Kali Praga. Tidak begitu banyak orang yang menyeberang. Ada sebuah rakit yang berhenti menepi ditambatkan pada satangnya yang ditancapkan pada pasir tepian.
“Rakit itu?” desis Pandan Wangi.
“Tidak ada tukang satangnya,” sahut Swandaru. Namun beberapa puluh langkah di pasir tepian, mereka melihat dua orang laki-laki duduk sambil memegangi masing-masing sebungkus nasi. Nampaknya mereka adalah tukang satang dari rakit yang ditambatkan itu.
“Mereka baru makan,” berkata Swandaru.
Dengan demikian, maka mereka menunggu rakit yang sedang meluncur dari seberang. Di atasnya hanya ada empat orang saja yang duduk terkantuk-kantuk. Panas matahari memang serasa membakar ubun-ubun. Dua Orang tukang satang yang mengenakan caping bambu, menekankan satangnya ke dasar Kali Praga. Sekali-sekali mereka mengusap keringat mereka yang mengalir membasahi pakaian mereka yang juga basah tepercik oleh air Kali Praga.
Ketika rakit itu telah merapat di tepian sebelah timur, maka keempat orang penumpangnya berloncatan turun. Sementara itu Pandan Wangi dan Swandaru menuntun kudanya naik ke atas rakit itu, bersama dua orang yang lain.
Beberapa saat kemudian, mereka pun telah turun dari rakit itu di sisi sebelah barat Kali Praga.
Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa berada di bumi kelahirannya. Tanah Perdikan Menoreh.
Swandaru dan Pandan Wangi tidak segera naik ke atas punggung kudanya. Perlahan-lahan mereka melangkah di atas pasir tepian yang basah. Namun ketika kemudian mereka mulai naik ke atas tebing yang landai, maka terasa kaki mereka mulai disengat panasnya pasir yang dipanggang sinar matahari.
Baru beberapa saat kemudian mereka berdua meloncat naik ke punggung kuda mereka Perlahan-lahan kedua ekor kuda itu berjalan meninggalkan Kali Praga yang airnya masih saja berwarna lumpur.
Sejenak kemudian keduanya mulai melarikan kuda mereka di jalan-jalan bulak Tanah Perdikan Menoreh.
“Alangkah segarnya angin yang bertiup agak kencang ini,” desis Pandan Wangi.
Swandaru tersenyum. Katanya, “Ya. Segarnya angin tanah perdikan.”
Pandan Wangi menarik nafas panjang.
Beberapa saat kemudian, maka kuda-kuda mereka pun berlari semakin cepat. Kuda Pandan Wangi berlari di depan, kemudian disusul kuda Swandaru. Dua ekor kuda yang terhitung besar dan tegar. Kedua-duanya dibeli dari Ki Ambara.
Ketika Swandaru dan Pandan Wangi memasuki jalan utama yang menuju ke padukuhan induk, maka matahari sudah menjadi semakin rendah. Ternyata mereka tertahan cukup lama di perjalanan selain mereka memang memerlukan waktu untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat
Kedatangan Pandan Wangi dan Swandaru di Tanah Perdikan Menoreh di sambut dengan gembira. Ki Gede yang sudah menjadi semakin tua, menekan dadanya melihat anak dan menantunya nampak rukun setelah mengalami guncangan karena tiupan angin pusaran yang cukup keras.
“Mari, mari Ngger,” Ki Gede langsung menyongsong anak dan menantunya, turun ke halaman.
Swandaru membungkuk hormat. Sedangkan Pandan Wangi langsung mencium tangan ayahnya. Terasa bahwa pelupuk mata Pandan Wangi menjadi basah dan mengalir ke pipinya, sehingga tangan Ki Gede pun menjadi basah pula
Keduanya pun kemudian naik ke pendapa. Swandaru duduk di pringgitan bersama Ki Gede, sementara Pandan Wangi pun langsung masuk ke ruang dalam. Rasa-rasanya ia menjadi demikian rindunya ‘melihat bagian dalam rumah tempat ia dilahirkan.
Baru kemudian, Pandan Wangi menyusul Swandaru duduk di pringgitan setelan ayahnya dan Swandaru saling menanyakan keselamatan masing-masing.
“Sudah agak lama aku menunggu-nunggu kedatangan kalian,” berkata Ki Gede.
Swandaru menunduk sambil menjawab, “Maaf Ayah, ada ber-macam-macam kesibukan yang datang susul-menyusul. Terakhir kami mendapat keterangan bahwa orang-orang yang ingin menegakkan kembali perguruan Kedung Jati telah merambah sampai ke Sangkal Putung.”
Ki Gede mengerutkan dahinya. Katanya, “Apakah mereka masih belum jera. Mereka telah dihancurkan di sini.”
“Ya, Mereka sudah dihancurkan di sini. Tetapi nampaknya mereka ingin mencoba mengintip Mataram dari sebelah timur.”
Ki Gede menarik nafas panjang. Dengan nada berat ia pun bertanya, “Apakah kunjunganmu ada hubungannya dengan itu?”
“Tidak Ayah. Tidak ada hubungannya. Aku merasa akan dapat mengatasinya.”
“Jadi, apakah kau hanya sekedar berkunjung atau membawa masalah penting?”
“Tidak ada masalah apa-apa Ayah. Kami hanya ingin berkunjung karena sudah agak lama kami tidak datang kemari. Terutama aku.”
“Oh, Syukurlah.”
“Aku juga ingin minta maaf kepada Ayah.”
“Kenapa?”
Swandaru tersenyum. Katanya, “Mataku agak kabur beberapa waktu yang lalu.”
Ki Gede pun tersenyum pula. Sementara Pandan Wangi menunduk dalam-dalam.
“Aku sudah melupakannya. Pandan Wangi pun tentu sudah melupakannya pula.”
Pandan Wangi tidak menyahut. Hanya kepalanya sajalah yang mengangguk perlahan.
“Terima kasih atas kebesaran jiwa Ayah dan Pandan Wangi.”
“Sudahlah. Sekarang, ceritakan tentang peningkatan kesejahteraan rakyatmu saja. Mungkin kau mempunyai cara-cara yang dapat diuapkan di sini.”
Swandaru menarik nafas dalam-dalam.
“Kami masih belum melangkah lebih jauh dari tanah perdikan ini, Ayah. Agaknya tanah perdikan ini juga maju dengan pesat meskipun kadang-kadang masih saja timbul persoalan yang gawat di sini.”
“Mungkin sisi lain dari pertanian?”
Swandaru termangu-mangu sejenak. Sementara itu, minuman hangat dan makanan pun dihidangkan.
Swandaru memang bercerita serba sedikit tentang usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan kademangannya. Namun seperti yang dikatakannya, Sangkal Putung memang tidak lebih maju dari Tanah Perdikan Menoreh. Di hari-hari terakhir, Menoreh berhasil menyusul ketinggalannya.
Namun dalam pembicaraan itu, Swandaru sama sekali masih belum menyinggung keperluannya yang sebenarnya. Bahkan ketika Swandaru mengatakan bahwa esok ia ingin bertemu dengan Agung Sedayu dan Sekar Mirah, Swandaru itu pun berkata, “Aku juga ingin memperingatkan Sekar Mirah. Bukankah ia salah seorang yang memegang pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Aku ingin memperingatkannya agar ia tidak terjebak.”
“Adikmu itu cukup berhati-hati, Swandaru,” berkata Ki Gede, “sebelum orang-orang itu menyerang tanah perdikan, mereka telah mencoba menghubungi Sekar Mirah. Bahkan berkali-kali.”
“Sekar Mirah juga sudah mengatakannya, Ayah. Tetapi aku masih ingin memperingatkan, bahwa orang-orang yang mengaku berkepentingan dengan perguruan Kedung Jati itu adalah orang-orang yang licik. Mungkin mereka sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan perguruan itu sebelumnya. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, mereka mengaku bagian dari perguruan itu.”
“Sekar Mirah menyadarinya.”
“Syukurlah. Tetapi Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu harus tetap berhati-hati. Mereka dapat mempergunakan segala cara untuk menjebak Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu. Mungkin dengan cara yang sangat lembut sehingga sama sekali tidak disadari, bahwa mereka telah masuk ke dalam wuwu sehingga sulit untuk keluar.”
“Tidak ada jeleknya kau memberinya peringatan, Swandaru.”
“Ya, Ayah. Tentu saja dengan cara yang tidak menyinggung perasaan Kakang Agung Sedayu, karena aku tahu, betapa lembutnya hati Kakang Agung Sedayu itu.”
Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, “Ya. Tetapi itu sudah men-jadi ciri wanci. Bawaan sejak lahirnya.”
“Tetapi ada yang berubah pada Kakang Agung Sedayu, Ayah.”
“Apa?”
“Juga ciri bawaannya. Kakang Agung Sedayu adalah seorang penakut sampai masa remajanya. Ia juga seorang yang rendah diri, yang tidak menyadari akan kemampuannya sendiri.”
“Ya. Sekarang tidak lagi. Bahkan Angger Agung Sedayu merupakan seorang lurah prajurit yang mumpuni.”
“Ya. Ia telah diangkat menjadi lurah dan memimpin satu pasukan justru dari pasukan khusus. Tetapi sayang. Justru karena itu, maka Kakang Agung Sedayu pun telah berhenti.”
“Berhenti? Maksudmu?”
“Kakang Agung Sedayu sudah merasa dirinya benar-benar mumpuni. Ia telah terbius sanjungan orang-orang di sekelilingnya sehingga Kakang Agung Sedayu tidak lagi berniat untuk mengembangkan ilmunya. Menurut pendapatku, Kakang Agung Sedayu beberapa tahun yang lalu, Kakang Agung Sedayu sekarang dan Kakang Agung Sedayu beberapa tahun yang akan datang, tetap tidak akan berubah. Ia akan tetap seperti Kakang Agung Sedayu yang kita lihat sekarang. Padahal aku sudah beberapa kali memperingatkannya, sementara kesempatan juga ada padanya.”
Ki Gede mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menyahut. Sementara itu Pandan Wangi menjadi gelisah. Setiap kali ia mendengar suaminya berbicara tentang Agung Sedayu, jantungnya menjadi berdebar-debar. Ia tahu, bahwa suaminya salah menilai saudara seperguruannya itu. Tetapi sulit baginya untuk meluruskannya. Jika ia mencobanya, maka akan dapat timbul salah paham. Pandan Wangi seakan-akan telah merendahkan kemampuan suaminya sendiri.
Pandan Wangi menarik nafas panjang ketika pembicaraan antara ayah dan suaminya itu bergeser. Mereka mulai membicarakan tentang musim dan kemungkinan Kali Praga banjir.
Beberapa saat kemudian, maka Ki Gede pun telah mempersilakan Swandaru dan Pandan Wangi untuk beristirahat. Bilik yang biasa mereka pergunakan di rumah itu sudah dibersihkan pula.
“Mungkin Angger Swandaru akan mandi supaya tubuhnya terasa segar,” berkata Ki Gede.
“Terima kasih Ayah,” sahut Swandaru.
Agung Sedayu dan Sekar Mirah mendengar kedatangan Swandaru dan Pandan Wangi, ketika malam sudah mulai turun. Sekar Mirah memang agak ragu, apakah mereka akan menemui Swandaru dan Pandan Wangi malam itu, atau esok pagi. Namun ternyata Agung Sedayulah yang mengajak Sekar Mirah pergi ke rumah Ki Gede, “Masih belum terlalu malam.”
Sekar Mirah mengangguk kecil. Katanya, “Marilah. Tetapi tidak terlalu lama. Kakang Swandaru dan Mbakayu Pandan Wangi tentu letih.”
Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab, “Baiklah. Kita akan segera pula.”
Kedatangan Agung Sedayu dan Sekar Mirah diterima oleh Swandaru dan Pandan Wangi dengan akrab. Mereka pun kemudian duduk di pringgitan bersama Ki Gede Menoreh.
“Kakang Swandaru dan Mbakayu Pandan Wangi tentu letih,” berkata Sekar Mirah, “kami tidak akan terlalu lama.”
“Tidak,” Swandaru tertawa, “perjalanan yang menyenangkan. Kami menempuh perjalanan seenaknya saja. Beberapa kali kami beristirahat. Kuda-kuda kamilah yang letih.”
Setelah mereka saling mempertanyakan keselamatan keluarga masing-masing, maka pembicaraan mereka pun menjadi riuh. Ke sana kemari. Dari jenis padi yang terbanyak ditanam sampai hama yang mengganggu batang kelapa. Mereka pun berbicara tentang keamanan dan kesejahteraan pula. Tentang penyakit dan tentang musim.
Dalam pada itu, maka Swandaru pun berkata, “Aku sebenarnya merencanakan esok akan mengunjungi kalian. Ada pesan yang ingin aku sampaikan. Tetapi karena kalian sudah datang lebih dahulu sekarang, maka aku kira tidak ada salahnya aku membicarakannya sekarang.”
Agung Sedayu dan Sekar Mirah saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Agung Sedayu pun berkata, “Katakan, Adi Swandaru. Bukankah sama saja besok atau sekarang?”
Swandaru tersenyum. Katanya, “Tidak penting. Hanya satu peringatan yang terutama bagi Sekar Mirah.”
“Maksud Kakang?”
“Orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu sekarang sudah merambah sampai ke Sangkal Putung. Setelah mereka dihancurkan di sini, agaknya mereka mencoba mencari jalan lain.”
“Oh,” Sekar Mirah mengangguk-angguk.
“Maksudku, aku hanya ingin mengatakan, bahwa sebenarnya tanah perdikan ini belum berhasil menghancurkan mereka sampai tuntas.”
“Ya,” Agung Sedayu mengangguk. Katanya, “Sebagian dari mereka memang berhasil melarikan diri.”
“Nah, mereka yang lolos dari tangan pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh yang dibantu oleh para prajurit Pajang itu agaknya masih merasa cukup kuat. Mereka agaknya sedang mencoba menyusun kekuatan untuk pada suatu saat bangkit kembali.”
“Memang satu kemungkinan,” sahut Agung Sedayu.
“Yang jelas, gerakan mereka sudah nampak di sekitar Sangkal Putung dan Jati Anom.”
“Apakah Kakang Untara sudah mengetahuinya?”
“Sudah. Pasukan Mataram di Jati Anom sudah siaga menghadapi gerakan itu. Tetapi kita tahu, bahwa kekuatan yang sebenarnya di Jati Anom itu bukan kekuatan yang cukup besar.”
Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Sementara Swandaru berkata selanjutnya, “Di Jati Anom tidak ada seorang senapati yang memiliki ilmu yang memadai. Meskipun demikian, Kekuatan Kakang Untara di Jati Anom memang harus diperhitungkan oleh mereka yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati.”
Swandaru berhenti sejenak. Kemudian ia pun melanjutkannya, “Tetapi agaknya perhatian orang-orang yang merasa pewaris perguruan Kedung Jati itu terbesar ditujukan kepada kekuatan para pengawal di Sangkal Putung. Agaknya mereka menganggap bahwa kekuatan para pengawal di Sangkal Putung cukup besar dan harus benar-benar diperhitungkan. Apalagi jika kekuatan di Sangkal Putung dan Jati Anom itu bergabung. Maka mereka akan menghadapi kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang telah menghancurkan mereka di tanah perdikan ini.”
Sekar Mirah mengangkat wajahnya. Namun Agung Sedayu justru mengangguk-angguk.
Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berkata apa-apa.
Sementara itu Swandaru pun berkata selanjurnya, “Nah, karena itu, aku ingin berpesan kepada Sekar Mirah. Bukankah kau salah seorang dari murid-murid Kedung Jati yang justru memiliki tongkat kepemimpinan?”
Sekar Mirah mengangguk sambil menjawab, “Ya, Kakang.”
“Karena itu kau harus berhati-hati. Mereka akan datang membujukmu dengan cara yang sangat lembut. Mungkin sekali kau tidak merasakan bujukan itu. Namun tiba-tiba saja kau sudah terjebak ke dalam satu keadaan yang tidak dapat kau ingkari lagi. Sehingga dengan demikian, mereka tinggal memerasmu. Suka atau tidak suka.”
Sekar Mirah memandang wajah kakaknya yang tampak ber-sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh pula Sekar Mirah itu pun berkata, “Aku mengerti, Kakang. Aku akan berhati-hati.”
“Suamimu adalah seorang lurah prajurit,” berkata Swandaru, “jika kau terjebak, maka suamimu akan ikut terjebak pula. Bahkan mungkin kalian harus membayar dengan sangat mahal. Prajurit dari pasukan khusus di barak Kakang Agung Sedayu akan dapat menjadi taruhan.”
“Ya, Kakang.”
“Aku minta Kakang ikut menjaga agar Sekar Mirah tidak terjebak. Kakang Agung Sedayu mempunyai wawasan yang jauh lebih luas karena tugas dan pengalaman Kakang.”
“Aku akan berusaha Adi Swandaru.”
“Sekali Sekar Mirah masuk dalam jebakan, maka lepaslah segala perhitungan dan pertimbangan nalar. Sekar Mirah harus memenuhi semua perintah-perintah yang diberikan oleh orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu.”
“Terima kasih atas peringatan ini Adi Swandaru. Sebelum terjadi pertempuran yang terhitung besar bagi Tanah Perdikan Menoreh, Sekar Mirah memang sudah beberapa kali didatangi oleh orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu. Bahkan Sekar Mirah pernah ditawari untuk menjadi salah seorang dari dua pemimpin tertinggi dari perguruan itu. Tetapi Syukurlah, bahwa Sekar Mirah tidak terbius oleh bujukan-bujukan itu, sehingga ia selamat dari cengkeraman orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu.”
“Mereka tidak akan berhenti sampai sekian.”
“Ya.”
“Jika dengan kasar mereka gagal, mereka akan menjebaknya dengan cara yang lebih halus.”
“Ya.”
“Bahkan dengan licik dan tidak tahu malu.”
“Ya.”
“Untuk selanjutnya, kami akan selalu menghubungi tanah perdikan ini,” berkata Swandaru kemudian, “kami akan memberikan keterangan-keterangan yang perlu. Terutama untuk melawan cara-cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya itu.”
“Terima kasih,” ulang Agung Sedayu, “kami pun akan memberikan keterangan-keterangan yang perlu seandainya ada usaha-usaha untuk membujuk dan bahkan menjebak Sekar Mirah.”
“Kita memang harus selalu berhubungan.”
Agung Sedayu masih saja mengangguk-angguk. Sementara Sekar Mirah berdesis, “Kadang-kadang jantungku berdegup semakin keras jika aku mengingat usaha-usaha orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu. Apalagi akhirnya aku tahu, bahwa perguruan Kedung Jati itu sekedar kedok belaka untuk mencapai satu tujuan yang lebih jauh.”
Swandaru mengerutkan dahinya. Sementara Sekar Mirah berkata selanjutnya, “Kakang Swandaru. Pada saat-saat menjelang perang yang terhitung besar yang terjadi di Tanah Perdikan Menoreh, aku pernah menjadi salah seorang yang harus mendapat pengawasan yang khusus oleh para penguasa di Mataram, justru karena aku adalah salah seorang pemegang sepasang tongkat pertanda pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Namun akhirnya Mataram mengakui bahwa aku tidak berkhianat terhadap Mataram. Sementara orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan paugeran.”
Swandarulah yang kemudian mengangguk-angguk.
“Perguruan Kedung Jati itu hanya dipergunakan sebagai landasan untuk satu penggapaian yang jauh. Tanah perdikan ini pun merupakan sasaran antara, karena sasaran yang sebenarnya adalah Mataram.”
“Apa yang mereka andalkan, sehingga mereka berani memandang ke arah Mataram?”
“Jumlah mereka cukup banyak, pendukung mereka cukup banyak pula. Jika mereka akan bangkit, mereka tentu akan berhubungan lagi dengan orang-orang Jipang, orang-orang Pati, orang-orang Demak yang kecewa, bahkan mereka akan menghimpun kekuatan di sebelah utara Gunung Kendeng.”
Swandaru termangu-mangu sejenak. Ternyata Sekar Mirah mempunyai wawasan cukup luas.
“Tentu suaminyalah yang mengajarinya,” berkata Swandaru di dalam hatinya.
Swandaru itu pun kemudian sambil mengangguk-angguk berkata, “Agaknya memang itulah yang akan terjadi. Karena itulah maka kita harus menjadi sangat berhati-hati terhadap mereka.”
“Ya, Kakang.”
“Baiklah,” berkata Swandaru kemudian, “mudah-mudahan kita tidak akan lengah sehingga mereka akan dapat menyusup masuk ke dalam tubuh kita dengan cara yang lebih berbahaya dari sebuah serangan terbuka.”
“Ya, Kakang,” sahut Sekar Mirah.
Swandaru masih memberikan beberapa pesan lagi tentang kemungkinan buruk yang dapat terjadi jika tanah perdikan menjadi lengah.
Namun Swandaru sendiri masih belum mengatakan, keperluannya yang sebenarnya. Swandaru tidak tergesa-gesa, sehingga kesan yang tersirat adalah kesungguhan. Bukan sekedar gagasan yang singgah tanpa dipertimbangkan masak-masak.
Namun seperti yang dikatakan oleh Sekar Mirah dan Agung Sedayu, mereka tidak terlalu lama berada di rumah Ki Gede. Setelah beberapa lama mereka berbincang, maka Sekar Mirah dan Agung Sedayu pun segera minta diri.
“Kakang Swandaru dan Mbakayu Pandan Wangi tentu letih,” berkata Sekar Mirah, “Silakan beristirahat. Besok kita masih mempunyai banyak waktu untuk berbincang tentang banyak hal.”
“Kami tidak merasa letih,” sahut Pandan Wangi, “kami hanya duduk saja di atas punggung kuda.”
Pandan Wangi tersenyum. Ia tahu bahwa Sekar Mirah pun seorang penunggang kuda sehingga ia tahu benar, bahwa menunggang kuda pun dapat juga menjadi letih.
Ki Gede yang ikut menemui mereka pun berkata, “Kenapa begitu tergesa-gesa Ngger?”
“Besok kami akan datang lagi, Ki Gede,” sahut Agung Sedayu.
Namun Swandaru pun berkata, “Besok sore akulah yang akan pergi ke rumahmu. Aku ingin berkunjung ke sana. Tetapi pagi hari kau tentu pergi ke barak.”
Agung Sedayu tersenyum. Katanya, “Silakan. Kami menunggu ke-datanganmu dengan senang hati.”
Sepeninggal Agung Sedayu dan Sekar Mirah, Swandaru masih berbincang beberapa lama dengan Ki Gede. Namun kemudian Ki Gede pun mempersilakan Swandaru dan Pandan Wangi untuk masuk ke ruang dalam.
“Kita duduk di dalam saja,” berkata Ki Gede, “angin mulai terasa dingin.”
Dalam pada itu, di perjalanan pulang, Sekar Mirah sempat berkata kepada Agung Sedayu, “Kakang Swandaru masih saja menganggap kita seperti kanak-kanak. Pesannya yang panjang dan terperinci kadang-kadang membuat aku tidak telaten.”
Agung Sedayu tersenyum. Katanya, “Bukankah kau adiknya? Kau tentu mengenal sifat dan watak kakakmu dengan baik.”
Sekar Mirah mengangguk. Namun katanya, “Meskipun demikian, seharusnya Kakang Swandaru itu pun berubah. Kami sudah menjadi semakin tua. Kakang Swandaru pun menjadi semakin tua. Pada suatu saat Kakang Swandaru harus melihat kenyataan tentang dirimu, Kakang.”
“Tentang apa?”
Api di Bukit Menoreh
Jilid IV – 27
Bagian 2 dari 3
“Kakang Swandaru masih saja merasa dirinya mempunyai banyak kelebihan dari Kakang Agung Sedayu.”
“Bukankah itu tidak mengganggu?”
“Memang tidak. Tetapi salah penilaian itu pada suatu saat akan terasa sangat pahit bagi Kakang Swandaru.”
“Karena itu, aku berusaha untuk tidak membuat perasaan Swandaru menjadi pahit.”
Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia kenal sifat dan watak kakaknya. Ia pun mengenal sifat dan watak suaminya.
“Sudahlah,” berkata Agung Sedayu, “Kita tahu, bahwa maksud Adi Swandaru itu baik. Ia tidak ingin terjadi bencana yang lebih besar di tanah perdikan ini melampaui perang yang baru saja terjadi. Jika orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu berhasil menjebakmu dengan cara yang sangat rumit dan licik, maka akibatnya akan buruk sekali.”
Sekar Mirah mengangguk-angguk.
Ketika mereka sampai di rumah, Ki Jayaraga, Glagah Putih dan Rara Wulan duduk di ruang dalam. Demikian Agung Sedayu dan Sekar Mirah masuk, maka mereka pun ikut pula duduk.
Demikian mereka duduk, maka Ki Jayaraga pun berkata, “Empu Wisanata dan Nyi Dwani baru saja pulang.”
“Mereka datang kemari?”
“Ya. Mereka datang kemari. Mereka mendengar bahwa kakak Nyi Lurah datang ke tanah perdikan. Mereka mengira bahwa kakak Nyi Lurah itu berkunjung kemari.”
“Besok mereka akan datang kemari.”
Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, “Besok, jika aku bertemu di sawah, akan aku katakan kepada Empu Wisanata. Ia ingin bertemu dengan kakak Nyi Lurah.”
“Biarlah besok ia datang kemari.”
Glagah Putihlah yang kemudian bertanya, “Apakah Kakang Swandaru itu tidak membawa oleh-oleh?”
Semua berpaling ke arah Glagah Putih. Hampir serentak mereka pun tertawa. Di sela-sela tertawanya Agung Sedayu itu pun berkata, “Jadi, oleh-olehnya itulah yang selalu kau ingat-ingat?”
Hampir saja Glagah Putih menjawab, “Kalau bukan oleh-olehnya, lalu apanya? Swandaru itu tidak ada apa-apanya.”
Tetapi untunglah ia segera teringat, bahwa Swandaru itu adalah kakak Nyi Lurah Sekar Mirah. Karena itu, maka Glagah Putih itu tidak menjawab, ia hanya tertawa saja seperti yang lain.
Ketika yang lain sudah berada di dalam biliknya, Agung Sedayu dan Sekar Mirah masih saja berbincang tentang kedatangan Swandaru dan Pandan Wangi yang tiba-tiba saja. Dengan nada berat Sekar Mirah itu pun berkata, “Agaknya Kakang Swandaru mempunyai keperluan lain. Ia tentu tidak hanya sekedar datang untuk memberi peringatan kepada kita, agar kita berhati-hati.”
“Mungkin. Tetapi agaknya Adi Swandaru menunggu saat yang paling tepat untuk membicarakannya.”
“Mungkin besok.”
Agung Sedayu hanya mengangguk-angguk saja.
Keduanya pun kemudian terdiam. Baru beberapa saat kemudian mereka pun masuk ke dalam bilik mereka.
Di keesokan harinya, seperti biasa, Agung Sedayu pun meninggalkan rumahnya pergi ke barak untuk menunaikan tugasnya. Sementara itu, yang lain pun sibuk dengan tugas masing-masing.
Di belakang, Glagah Putih sibuk mengisi pakiwan, sementara Sukra membelah kayu bakar.
Demikian pakiwan itu penuh, maka Glagah Putih pun berkata kepada Sukra, “He, ambil kelenting. Kita mengisi gentong di dapur.”
Sukra mengerutkan dahinya. Diletakkan kapaknya. Diambil kelenting di sebelah pintu dapur. Namun ketika ia berdiri menunggu Glagah Putih mengisi kelenting, Sukra pun berkata, “Kerja perempuan.”
“Siapa yang kau maksud?”
“Mbakayu Sekar Mirah atau Rara Wulan?”
“He?”
Tetapi Sukra justru berkata, “Cepat. Kenapa kelenting itu tidak segera kau isi?”
Glagah Putih menarik nafas panjang. Namun dituangnya air yang ditimbanya dari sumur itu ke dalam kelenting.
Sementara itu Ki Jayaraga telah berangkat ke sawah sambil membawa cangkul. Ia sudah mengingat-ingat, jika ia bertemu dengan Empu Wisanata ia ingin memberitahukan, bahwa jika ia bertemu dengan Swandaru, kakak Sekar Mirah, sore nanti akan pergi ke rumah Agung Sedayu.
“Aku akan pergi ke rumah Ki Lurah,” sahut Empu Wisanata ketika Ki Jayaraga benar-benar menyampaikan kepadanya.
“Datanglah. Sekedar berbincang-bincang,”
Sebenarnyalah, di sore hari, ketika Agung Sedayu sudah berada di rumahnya, Swandaru dan Pandan Wangi telah datang berkunjung sebagaimana dikatakannya semalam.
Empu Wisanata sebagaimana dikatakannya, telah datang berkunjung pula ke rumah Agung Sedayu bersama Nyi Dwani.
Keduanya memang sempat bertemu dan berbicara dengan Swandaru dan Pandan Wangi.
“Sebelumnya kami tinggal di rumah ini pula,” berkata Empu Wisanata, “tetapi sekarang kami sudah tinggal di rumah sendiri. Rumah yang kami dapat atas kemurahan hati Ki Gede Menoreh serta Ki Lurah dan Nyi Lurah.”
“Bukan kami,” sahut Agung Sedayu, “Ki Gede dan para bebahu tanah perdikan ini.”
Empu Wisanata tertawa katanya, “Tetapi pada mulanya, karena kebaikan hati Ki Lurah.”
“Kenapa pada mulanya?” bertanya Sekar Mirah.
Empu Wisanata masih saja tertawa. Bahkan Nyi Dwani, Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun tertawa pula.
Dalam pada itu selagi mereka berbincang di pringgitan, Glagah Putih yang baru pulang dari padukuhan sebelah, menuntun kudanya melintasi halaman. Swandaru yang melihat kuda Glagah Putih mengerutkan dahinya Ia sudah melihat kuda itu sebelumnya. Tetapi setelah ia menukar kudanya dengan kuda yang dianggap sangat baik, ternyata masih belum sebaik kuda Glagah Putih itu.
Swandaru yang setiap kali berbicara tentang kuda dengan Ki Ambara di luar sadarnya berdesis, “Kuda yang sangat baik.”
“Bukankah kuda itu sudah lama dimiliki oleh Glagah Putih?”
“Aku dan Pandan Wangi mempunyai kuda yang sangat baik. Bahkan di Sangkal Putung dan sekitarnya, tidak ada yang menyamainya. Namun agaknya masih belum sebaik kuda Glagah Putih itu.”
“Kakang membeli kuda yang baru?” bertanya Sekar Mirah sekedar untuk menanggapinya.
“Ya. Aku membeli kuda dari seorang pedagang kuda yang terbaik. Ki Ambara. Ia selalu mendapatkan kuda-kuda yang baik. Tetapi kuda yang kami beli adalah kuda-kuda yang terbaik,” berkata Swandaru kemudian, “tetapi belum sebaik kuda Glagah Putih,” ”
“Bukankah Adi Swandaru pernah melihat kuda itu?”
“Ya. Tetapi waktu itu aku tidak begitu menghiraukannya.”
Agung Sedayu tertawa. Katanya, “Nampaknya sekarang perhatian Adi Swandaru terhadap kuda lebih besar lagi, sehingga seakan-akan baru sekarang melihat bahwa kuda Glagah Putih adalah kuda yang besar dan tegar.”
Swandaru mengangguk-angguk sambil tertawa pula. Katanya, “Ya. Agaknya memang demikian.”
Dalam pada itu, untuk beberapa saat lamanya mereka berbicara tentang kuda. Apalagi ketika Glagah Putih ikut pula menemui Swandaru dan Pandan Wangi.
Meskipun sebenarnya Glagah Putih agak segan menemuinya, karena setiap kali Swandaru hanya mencela ilmu Agung Sedayu saja, tetapi untuk menjaga perasaan Sekar Mirah, maka ia pun duduk pula di pendapa.
Namun, ternyata saat itu Swandaru tidak sedang menggurui Agung Sedayu, tetapi Swandaru sedang berbicara tentang kuda.
“Besok jika aku kembali ke Sangkal Putung, aku akan menemui Ki Ambara. Aku akan minta dicarikan kuda sebaik kuda Glagah Putih.”
Glagah Putih tersenyum. Katanya, “Mudah-mudahan Kakang Swandaru mendapatkannya.”
Namun setelah mereka menghirup minuman dan makan-makanan yang disuguhkan, Swandaru itu pun berkata kepada Agung Sedayu, “Kakang. Sebenarnya ada sesuatu yang penting aku bicarakan dengan Kakang. Tetapi aku minta maaf, bahwa pembicaraan ini hanyalah pembicaraan antara kita berempat. Aku dan Pandan Wangi, Kakang Agung Sedayu dan Sekar Mirah.”
“Baiklah,” sahut Ki Jayaraga, “aku akan mengajak Empu Wisanata ke serambi gandok, sedangkan Nyi Dwani biar menemani Angger Rara Wulan di dapur.”
“Aku minta maaf,” ulang Swandaru.
Dengan demikian maka selain Swandaru, Pandan Wangi, Agung Sedayu dan Sekar Mirah, mereka yang berada di pringgitan itu pun beranjak pergi. Glagah Putih pun telah pergi ke belakang menemui Sukra yang baru mengupas kelapa.
“Kau baru saja memetik kelapa?” bertanya Glagah Putih.
“Ya.”
“Berapa buah?”
“Aku hanya menurunkan lima belas buah.”
Glagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Sukra bertanya -Apakah tamunya sudah pulang?”
“Belum.”
“Kenapa kau meninggalkan pringgitan?”
“Tidak apa-apa.”
Sukra tidak bertanya lagi. Ia pun membiarkan saja ketika Glagah Putih mengambil slumbat kelapa satu lagi dan membantu mengupas kelapa.
Sementara itu, Swandaru yang berada di pringgitan pun berkata, “Kakang Agung Sedayu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Sebelumnya aku belum mengatakan kepada siapa pun. Kepada Ki Gede pun aku belum menyampaikannya.”
Agung Sedayu dan Sekar Mirah mendengarkan kata-katanya sangat penting sehingga Swandaru minta mereka berbicara berempat saja. Bahkan persoalannya masih belum disampaikan kepada Ki Gede Menoreh.
Baru beberapa saat kemudian, Swandaru itu pun berkata, “Kakang Agung Sedayu. Kami sengaja datang menemui Kakang Agung Sedayu dan Sekar Mirah untuk minta pertimbangan kalian berdua.”
“Tentang apa, Adi?” bertanya Agung Sedayu.
“Kakang. Menurut pendapatmu, apakah Sangkal Putung termasuk satu lingkungan yang pernah berjasa bagi Mataram?”
Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab, “Ya Sangkal Putung telah banyak memberikan jasanya kepada Mataram.”
“Apakah jasa yang diberikan itu cukup bernilai?”
“Ya,” jawab Agung Sedayu tanpa mengerti maksud pertanyaan Swandaru.
“Kakang. Kami berdua mewakili rakyat Kademangan Sangkal Putung untuk menyampaikan satu permohonan kepada Kangjeng Panembahan Senapati. Tetapi sebelumnya aku ingin mendengar pendapat Kakang berdua. Menurut pendapatku, Kakang adalah orang yang mengenal dan dikenal baik oleh Kangjeng Panembahan Senapati.”
“Apa yang ingin Adi sampaikan itu?” dada Agung Sedayu dan Sekar Mirah menjadi berdebar-debar.
“Kakang. Bagaimana menurut pertimbangan Kakang, jika rakyat Tanah Perdikan Menoreh mengajukan permohonan kepada Kangjeng Panembahan Senapati, agar Kademangan Sangkal Putung mendapat ke-dudukan sebagai tanah perdikan?”
Agung Sedayu terkejut. Sekar Mirah pun terkejut pula, sehingga wajah perempuan itu menjadi tegang.
Agung Sedayu yang dengan cepat dapat menguasai perasaannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Apakah gagasan ini timbul dari Ki Demang Sangkal Putung?”
“Tidak. Tidak,” jawab Swandaru dengan serta-merta, “bahkan Ayah baru tahu ketika kami akan berangkat kemari.”
“Jadi?”
Swandaru menarik nafas dalam-dalam, sementara Pandan Wangi hanya menundukkan kepala saja. Sebenarnyalah bahwa Pandan Wangi tidak sependapat dengan suaminya. Tetapi menurut suaminya, para bebahu yang mewakili rakyat Sangkal Putung sudah sepakat untuk mengajukan permohonan kepada penguasa di Mataram, agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi tanah perdikan. Dengan demikian maka Pandan Wangi tidak dapat mencegah niat suaminya untuk menyampaikan keinginan itu ke Mataram serta keinginannya mendapat dukungan dari keluarga di Tanah Perdikan Menoreh.
Dalam pada itu, Swandaru itu pun berkata, “Kakang Agung Sedayu. Sebenarnyalah bahwa Ayah tidak mempunyai gagasan untuk mengusulkan agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Tetapi rakyat Sangkal Putunglah yang mengajukan gagasan itu kepada Ayah sementara rakyat Sangkal Putung telah memutuskan untuk mengutus aku ke Mataram, aku menganggap bahwa lebih baik aku pergi ke Tanah Perdikan Menoreh untuk minta pertimbangan dari keluarga di tanah perdikan ini.”
Agung Sedayu justru termangu-mangu sejenak. Ia tidak segera dapat menanggapi sikap para pemimpin di Kademangan Sangkal Putung yang penyampaiannya ke Mataram dibebankan kepada Swandaru.
Namun Sekar Mirahlah, yang kemudian justru bertanya, “Lalu bagaimana sikap Ayah?”
“Ayah tidak dapat menentang gagasan rakyat Sangkal Putung itu. Apalagi rakyat Sangkal Putung telah menetapkan aku untuk berangkat ke Mataram. Tetapi aku masih minta waktu untuk pergi ke Tanah Perdikan Menoreh lebih dahulu.”
“Sedangkan Kakang sendiri?”
“Apalagi aku, Sekar Mirah. Sedangkan Ayah pun tidak dapat menentangnya.”
“Adi Swandaru,” berkata Agung Sedayu kemudian, “apakah dasarnya rakyat Sangkal Putung minta agar Kademangan Sangkal Putung ditetapkan menjadi tanah perdikan?”
“Kakang,” berkata Swandaru kemudian, “rakyat Sangkal Putung menganggap bahwa kedudukan tanah perdikan itu lebih baik dari sebuah kademangan. Tanah perdikan dapat mengatur pajak bagi kepentingan tanah perdikan itu sendiri. Ikatannya dengan Mataram menjadi lebih longgar. tanah perdikan hanya diwajibkan memberikan upeti yang tidak diperhitungkan nilai upeti itu sendiri, karena pada dasarnya upeti hanyalah pertanda bahwa tanah perdikan itu masih berada di bawah lingkungan pemerintahan Mataram. Sehingga seberapa pun nilai upeti itu tidaklah menjadi soal.”
Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Swandaru berkata selanjutnya, “Sedangkan alasan rakyat Sangkal Putung untuk minta agar kademangannya ditetapkan menjadi tanah perdikan adalah, bahwa selama ini Sangkal Putung telah banyak berjasa kepada Mataram. Tidak kalah dengan Tanah Perdikan Menoreh.”
Pandan Wangi mengangkat wajahnya sekilas. Namun kemudian ia pun menunduk lagi. Katanya, “Tentu karena rakyat Sangkal Putung tidak tahu, keseimbangan jasa yang telah diberikan oleh beberapa daerah. Tetapi rakyat Sangkal Putung merasa bahwa mereka tidak memberikan jasa mereka sejauh dapat mereka lakukan.”
Swandaru mengerutkan dahinya. Sementara Sekar Mirah pun berkata, “Kita memang tidak tahu, apakah jasa sesuatu daerah lebih besar dibanding dengan daerah yang lain. Karena itu sulit untuk mengatakan bahwa satu daerah telah memberikan jasa lebih dari daerah yang lain sebagaimana dikatakan oleh Mbakayu Pandan Wangi. Mataramlah yang akan menilainya. Karena itu, Kakang. Apakah untuk menetapkan satu daerah menjadi tanah perdikan itu tidak ditentukan oleh Mataram?”
“Mungkin kau benar Sekar Mirah,” jawab Swandaru, “tetapi mungkin pula para pemimpin di Mataram tidak sempat memperhatikannya. Karena itu, maka ada baiknya kami minta perhatian itu. Meskipun akhirnya keputusan terakhir terserah kepada Mataram.”
“Kakang,” berkata Sekar Mirah kemudian, “Apakah Kakang tidak dapat meredakan keinginan rakyat Sangkal Putung itu?”
“Maksudmu?” bertanya Swandaru.
“Agar rakyat Sangkal Putung menyadari, bahwa tidak sebaiknya mereka mengajukan permohonan itu. Dengan demikian ada kesan, bahwa pengabdian yang di berikan oleh rakyat Sangkal Putung itu mempunyai pamrih tertentu. Bukan pengabdian yang ikhlas.”
Swandaru termangu-mangu sejenak. Pendapat Sekar Mirah sebagai salah seorang anak Demang Sangkal Putung dapat menyentuh hati Swandaru.
Untuk beberapa saat Swandaru terdiam. Namun kemudian ia pun bertanya, “Bagaimana pendapatmu, Kakang Agung Sedayu?”
“Adi Swandaru,” berkata Agung Sedayu, “menurut pendapatku, sebaiknya Sangkal Putung menunggu. Mataram tidak akan berpaling dari lingkungannya yang memang pantas untuk ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Mataram pun tentu sudah mempunyai patokan yang mapan. Jika Sangkal Putung mengajukan diri, maka seperti yang dikatakan oleh Sekar Mirah, bahwa jasa yang telah diberikan oleh Sangkal Putung justru akan dilupakan, karena pengabdiannya bukan pengabdian yang bersih. Tetapi pengabdian yang mempunyai pamrih.”
Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berpaling kepada Pandan Wangi dan bertanya, “Bagaimana pendapatmu Pandan Wangi?”
Pertanyaan Swandaru itu membuat Pandan Wangi bimbang. Namun kemudian ia memutuskan untuk menjawab sesuai dengan kata hatinya.
“Kakang, aku sependapat dengan Sekar Mirah. Bukannya aku tidak menginginkan Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan. Tetapi jika Sangkal Putung sendiri yang mengajukan permohonan, maka seakan-akan apa yang kita lakukan selama ini bukannya satu pengabdian yang tulus. Tetapi justru karena kita mempunyai pamrih agar kademangan kita ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan.”
Semula Pandan Wangi cemas, bahwa Swandaru menjadi tidak senang mendengar jawabnya. Namun ternyata Swandaru mengangguk-angguk sambil berdesis, “Jika demikian, maka rakyat Sangkal Putung perlu memikirkannya lagi.”
“Bagus, Kakang,” sahut Sekar Mirah, “aku sebagai salah seorang anak Demang Sangkal Putung, tentu senang jika kedudukan Sangkal Putung meningkat menjadi sebuah tanah perdikan jika itu memang dikehendaki oleh Mataram atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang maton. Tetapi tidak dengan mengajukan permohonan dengan cara apapun.”
Swandaru masih saja mengangguk-angguk. Katanya, “Baik. Baik. Jika demikian aku akan bertemu dan berbicara dengan para bebahu. Sangkal Putung tidak perlu minta untuk ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan, karena jika hal itu dianggap tepat, Mataram akan menetapkannya dengan sendirinya.”
“Ya Agaknya itulah yang terbaik, Kakang,” desis Sekar Mirah.
“Jika demikian, aku tidak akan berbicara dengan siapa-siapa lagi. Aku juga tidak akan berbicara dengan Ki Gede.”
“Agaknya memang tidak perlu, Kakang,” sahut Sekar Mirah.
Swandaru mengangguk-angguk. Namun demikian ia pun berkata, “Meskipun demikian, Kakang. Seandainya. Hanya seandainya ada kesempatan, apa salahnya jika Kakang mengingatkan para pejabat di Mataram untuk menilai Kademangan Sangkal Putung, apakah Kademangan Sangkal Putung pantas untuk ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan atau tidak.”
“Baiklah, Adi Swandaru. Jika demikian halnya, aku tidak berkeberatan. Soalnya tentu berbeda dengan mengajukan permohonan agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan.”
“Terima kasih, Kakang. Selanjutnya memang terserah kepada Kangjeng Panembahan Senapati.”
Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Pandan Wangi mengangguk-angguk. Mereka sependapat dengan sikap Swandaru yang terakhir.
Dengan demikian, maka Swandaru pun mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan Ki Gede Menoreh, apalagi minta dukungan atas permohonan Sangkal Putung untuk ditetapkan menjadi tanah perdikan.
Beberapa saat kemudian, maka matahari pun menjadi semakin rendah. Karena itu, maka Swandaru pun kemudian minta diri sebelum senja turun.
Kepada Empu Wisanata, Nyi Dwani, Ki Jayaraga, Glagah Putih dan Rara Wulan, Swandaru pun minta diri selagi masih belum gelap.
Sepeninggal Swandaru, seisi rumah Agung Sedayu serta Empu Wisanata dan Nyi Dwani telah duduk di Pringgitan. Tetapi Agung Sedayu dan Sekar Mirah sama sekali tidak menyebut sama sekali pembicaraan mereka dengan Swandaru dan Pandan Wangi. Sementara yang lain pun tidak bertanya, karena pembicaraan itu nampaknya memang rahasia
Beberapa saat kemudian, maka Empu Wisanata dan Nyi Dwani pun telah minta diri pula meninggalkan rumah Agung Sedayu.
Menjelang makan malam, Agung Sedayu dan Sekar Mirah duduk berdua di serambi rumahnya. Dengan nada rendah Sekar Mirah pun berkata, “Aku mengira bahwa tentu ada orang yang menyorongkan gagasan itu kepada Kakang Swandaru.”
“Mungkin. Tetapi mungkin juga gagasan itu gagasan yang sengaja dihembuskan kepada Adi Swandaru dengan tujuan yang kurang baik. Mungkin seseorang yang iri melihat perkembangan Sangkal Putung, sehingga jika Sangkal Putung mengajukan permohonan itu, maka nama kademangan itu menjadi cacat.”
Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, “Kakang Swandaru masih saja mudah menerima gagasan orang lain tanpa pertimbangan yang masak. Sementara Mbakayu Pandan Wangi agaknya tidak ingin menyinggung perasaan Kakang Swandaru. Apalagi setelah Kakang Swandaru merasa bersalah dan minta maaf kepadanya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.”
“Kita dapat mengerti, bahwa Pandan Wangi ingin membuat keluarganya tidak mengalami gangguan.”
“Ya Meskipun demikian, Mbakayu Pandan Wangi dapat saja menyampaikan pertimbangannya kepada Kakang Swandaru.”
Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun meskipun Swandaru mengurungkan niatnya, tetapi bahwa gagasan itu timbul di lingkungan orang-orang Kademangan Sangkal Putung, telah membuat Agung Sedayu harus merenunginya.
Dalam pada itu, meskipun Ki Jayaraga, Glagah Putih dan Rara Wulan bertanya-tanya di dalam hati, namun mereka tidak bertanya langsung kepada Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Sambil berbisik-bisik Rara Wulan memang bertanya kepada Glagah Putih, “Apakah yang mereka bicarakan?”
Glagah Putih menggeleng. Katanya, “Entahlah. Nampaknya penting dan rahasia.”
Rara Wulan tidak bertanya lebih lanjut. Tiba-tiba saja Sekar Mirah telah berada di dapur, membantu Rara Wulan menyiapkan makan malam mereka.
Dalam pada itu, seperti yang dikatakan oleh Swandaru, ia tidak menyampaikan persoalannya kepada Ki Gede. Swandaru dan Pandan Wangi sepakat untuk menunda atau bahkan membatalkan maksud mereka untuk minta penimbangan kepada Ki Gede, karena Swandaru bahkan ingin membicarakannya lagi dengan rakyat Sangkal Putung.
Dengan demikian maka bagi Ki Gede, Swandaru dan Pandan Wangi datang ke tanah perdikan untuk sekedar menengoknya.
“Pandan Wangi tentu sudah rindu kepadaku dan kepada tempat kelahirannya,” berkata Ki Gede di dalam hatinya.
Meskipun Swandaru membatalkan niatnya berbicara dengan Ki Gede tentang keinginannya menjadikan Sangkal Putung sebuah tanah perdikan, namun Swandaru tidak tergesa-gesa meninggalkan Tanah. Perdikan Menoreh. Swandaru dan Pandan Wangi masih bermalam beberapa malam lagi. Mereka menyempatkan diri untuk melihat-lihat kesuburan tanah perdikan. Mereka pun melihat-lihat lereng-lereng pegunungan yang ditumbuhi hutan yang termasuk lebat dan dihuni oleh binatang-binatang buas.
Bagi Swandaru dan Pandan Wangi, keberadaan mereka di Tanah Perdikan Menoreh, merupakan hari-hari yang sejuk. Swandaru benar-benar sempat beristirahat Ia tidak harus memikirkan kesibukan-kesibukan kerja sehari-hari. Di Tanah Perdikan Menoreh, Swandaru dan Pandan Wangi sempat menikmati segarnya angin yang semilir di sore hari tanpa digelisahkan oleh kerja yang tertunda.
Namun Swandaru dan Pandan Wangi tidak dapat terlalu lama berada di Tanah Perdikan Menoreh. Meskipun keduanya sempat merasakan ketenangan dan kedamaian di antara kesibukan orang-orang yang bekerja di sawah, namun mereka harus kembali ke Sangkal Putung.
Karena itu, maka setelah beberapa hari mereka berada di Tanah Perdikan Menoreh, maka ketika mereka bersama Ki Gede makan malam, Swandaru pun berkata, “Ayah. Kami sudah terlalu lama berada di tanah perdikan. Besok lusa, pagi-pagi sekali kami akan mohon diri.”
“Begitu tergesa-gesa?”
“Aku meninggalkan tugas-tugasku di Kademangan Sangkal Putung Ayah. Besok kami masih sempat minta diri kepada keluarga di tanah perdikan ini.”
Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara Pandan Wangi pun berkata, “Kami masih sempat mengunjungi Paman Argajaya, Prastawa dan Kakang Agung Sedayu untuk minta diri.”
Ki Gede Menoreh yang dapat mengerti kesibukan-kesibukan Swandaru di Kademangan Sangkal Putung itu pun berkata, “Baiklah. Besok kau masih mempunyai satu hari di tanah perdikan ini.”
Seperti yang dikatakan oleh Pandan Wangi, maka di keesokan harinya Swandaru dan Pandan Wangi sempat mengunjungi Ki Argajaya dan Prastawa untuk minta diri. Kemudian di sore hari mereka pergi ke rumah Agung Sedayu setelah Agung Sedayu pulang dari barak, juga untuk minta diri.
“Apakah besok Kakang akan berangkat pagi-pagi sekali?” berkata Sekar Mirah.
“Tidak pagi-pagi sekali. Kami akan berangkat pada saat matahari terbit.”
“Baiklah. Besok kami berdua akan berada di rumah Ki Gede menjelang matahari terbit.”
“Bukankah Kakang Agung Sedayu harus pergi ke barak?”
Tetapi Agung Sedayu pun menyahut, “Aku tidak harus datang terlalu pagi di barak.”
Swandaru tersenyum. Katanya, “Enaknya menjadi lurah prajurit. Yang lain harus menepati ketetapan, tetapi lurahnya dapat berbuat lain.”
Agung Sedayu tertawa. Katanya, “Tetapi bukankah tidak setiap hari?”
Yang lain pun tertawa pula.
Menjelang senja, maka Swandaru pun minta diri untuk kembali ke rumah Ki Gede. Kepada Ki Jayaraga, Glagah Putih dan Rara Wulan, Swandaru dan Pandan Wangi telah minta diri. Besok mereka akan kembali ke Kademangan Sangkal Putung.
Di malam terakhir Swandaru dan Pandan Wangi berada di tanah perdikan, rumah Ki Gede menjadi ramai. Ki Argajaya, Prastawa dan istrinya, bahkan Agung Sedayu dan Sekar Mirah esok pagi akan datang melepas kepergian Swandaru, telah berkunjung ke rumah Ki Gede. Mereka sempat berbincang-bincang sampai jauh malam. Sehingga akhirnya Ki Argajaya pun berkata, “Swandaru dan Pandan Wangi harus segera tidur. Mereka besok akan menempuh perjalanan yang panjang. Karena itu, aku minta diri. Aku mengucapkan selamat jalan kepada kalian berdua. Hati-hatilah di jalan. Mudah-mudahan kalian tidak menemui hambatan apapun.”
“Terima kasih, Paman. Doa Paman yang kami mohon menyertai perjalanan kami,” sahut Swandaru.
Bukan saja Ki Argajaya yang meninggalkan rumah Ki Gede. Tetapi tamu-tamu yang lain pun minta diri pula. Swandaru dan Pandan Wangi memang harus beristirahat karena esok pagi-pagi mereka akan meninggalkan Tanah Perdikan Menoreh.
Sepeninggal tamu-tamunya, maka Ki Gede pun berkata, “Beristirahatlah. Malam telah larut.”
Swandaru dan Pandan Wangi pun kemudian masuk ke dalam bilik mereka. Sementara malam pun menjadi semakin malam.
Seperti yang dikatakan, maka pagi-pagi sekali keduanya telah siap pula. Agung Sedayu dan Sekar Mirah benar-benar datang untuk melepas Swandaru dan Pandan Wangi yang akan kembali ke Sangkal Putung.
Demikianlah, ketika langit menjadi terang oleh bayangan cahaya matahari, maka Swandaru dan Pandan Wangi pun telah minta diri. Pandan Wangi mencium tangan ayahnya sambil mohon doa restu, agar di perjalanan mereka tidak mengalami gangguan apapun juga.
“Kami mohon diri Ayah,” desis Swandaru kemudian, “kami mohon doa restu Ayah menyertai kami serta bagi keluarga kami di Sangkal Putung dan cucu Ayah yang nakal itu.”
“Ajak cucuku kemari,” berkata Ki Gede, “aku sangat rindu kepadanya.”
“Pada kesempatan lain, kami akan membawanya. Ia tentu senang diajak naik kuda ke tanah perdikan ini. Tetapi sebelumnya ia harus mulai berlatih sedikit demi sedikit.”
“Jangan paksakan anak itu naik kuda sendiri,” berkata Ki Gede.
“Aku akan mencoba membawanya naik bersamaku, Ayah.”
Ki Gede tertawa. Katanya, “Aku akan pergi ke Sangkal Putung untuk menengok cucuku.”
“Betul Ayah?” bertanya Pandan Wangi.
“Ya.”
“Kapan Ayah akan pergi ke Sangkal Putung?”
“Aku belum dapat menentukan waktunya. Ayah sudah semakin tua. Karena itu, ayah harus benar-benar memperhitungkan keadaan kesehatan ayah sebelum ayah menentukan untuk berangkat ke Sangkal Putung.”
“Perjalanan ke Sangkal Putung memang panjang, Ayah. Tetapi Ayah dapat menempuh perjalanan dengan tidak tergesa-gesa. Mungkin Ayah harus bermalam di Mataram. Baru kemudian melanjutkan perjalanan di keesokan harinya.”
Ki Gede tertawa. Katanya, “Tentu aku masih cukup kuat berkuda langsung ke Sangkal Putung.”
Pandan Wangi pun tertawa. Katanya, “Maksudku, mungkin Ayah ingin juga melihat-lihat keadaan di sepanjang perjalanan yang sudah agak lama tidak Ayah lihat.”
“Baiklah,” berkata Ki Gede, “pada kesempatan lain aku akan benar-benar sampai di Sangkal Putung.”
Demikianlah, maka sejenak kemudian, Swandaru dan Pandan Wangi pun telah menuntun kudanya ke regol. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun kemudian berdiri di luar regol halaman. Ketika Swandaru dan Pandan Wangi naik ke punggung kudanya, maka Agung Sedayu pun berkata, “Kapan-kapan aku dan Sekar Mirah akan mengantar Ki Gede ke Sangkal Putung.”
“Benar Kakang?” bertanya Pandan Wangi.
“Ya,” Sekar Mirahlah yang menjawab, “Tentang waktunya, Ki Gede yang akan menentukan.”
“Aku dapat pergi kapan pun aku kehendaki. Ki Lurah Agung Sedayulah yang terikat oleh tugas-tugasnya.”
Agung Sedayu pun tertawa.
Demikianlah, maka sejenak kemudian Swandaru dan Pandan Wangi itu pun telah meninggalkan rumah Ki Gede Menoreh. Kuda mereka berlari tidak terlalu kencang. Demikian mereka keluar dari padukuhan induk, maka matahari pun telah terbit Cahayanya yang kekuning-kuningan memancar mewarnai batang padi yang hijau di bulak-bulak sawah yang luas. Daunnya terayun-ayun tertiup angin, seperti gelombang lembut yang mengalir berurutan menuju ke pantai.
Titik-titik embun masih bergayut di ujung daun bambu yang seakan-akan berjuntai di ujung padukuhan di depan mereka.
Ketika sinar matahari menjadi semakin menggatalkan kulit, maka kuda-kuda Swandaru dan Pandan Wangi pun berlari lebih kencang lagi.
Di sepanjang jalan selagi mereka masih berada di Tanah Perdikan Menoreh, Pandan Wangi sempat memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Ngarai yang datar, pegunungan yang semakin jauh mereka tinggalkan, parit-parit dengan airnya yang bening serta padukuhan-padukuhan yang hijau rimbun dengan pohon nyiur yang mencuat bertebaran di mana-mana.
Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya ke-sejahteraan rakyat tanah perdikan menjadi semakin tinggi, seperti juga ke-sejahteraan rakyat Sangkal Putung.
Kehidupan terasa tenang dan damai, meskipun diwarnai dengan gereget kerja yang tinggi.
Dalam pada itu, terasa sinar matahari semakin lama menjadi semakin panas. Mereka pun kemudian menjadi semakin dekat dengan Kali Praga.
Berbeda dengan saat mereka menyeberang dari timur, hari itu agak banyak orang yang akan menyeberang. Baik dari barat maupun dari timur Kali Praga. Semua rakit yang ada bergerak melintas silang menyilang. Ada orang-orang yang menunggu dengan sabar giliran mereka sambil duduk-duduk di pasir tepian.
Swandaru dan Pandan Wangi pun harus menunggu beberapa saat. Rakit yang merapat tidak dapat membawa mereka, karena beberapa orang sudah menunggu lebih dahulu.
Karena itu, mereka harus menunggu rakit yang masih berada di tengah-tengah Kali Praga
Tetapi Swandaru dan Pandan Wangi tidak tergesa-gesa.
Demikianlah, beberapa saat kemudian, Swandaru dan Pandan Wangi telah melanjutkan perjalanan mereka pula. Setelah menyeberangi Kali Praga, mereka pun melarikan kuda mereka. Panasnya matahari terasa semakin menyengat kulit.
Namun perjalanan Swandaru dan Pandan Wangi memang tidak terhambat. Meskipun demikian beberapa kali mereka berhenti untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat.
Namun sedikit lewat tengah hari, Swandaru dan Pandan Wangi sendiri juga memerlukan beristirahat untuk minum dan makan.
Namun Kademangan Sangkal Putung sudah tidak terlalu jauh lagi.
Ketika kemudian mereka memasuki sebuah padukuhan yang termasuk dalam lingkungan Kademangan Sangkal Putung, maka terasa udara yang sejuk seakan-akan menyusup sampai ke tulang.
Seperti ketika memasuki Tanah Perdikan Menoreh, Pandan Wangi pun merasa bahwa ia telah pulang. Pulang ke rumahnya. Pulang kepada keluarganya, kepada anaknya yang telah menunggunya.
Kedatangan Swandaru dan Pandan Wangi disambut oleh seluruh keluarga dengan gembira. Terlebih-lebih anak mereka yang langsung melekat di gendongan ibunya
“Ibu masih lelah,” berkata Ki Demang, “mari, bersama kakek saja.”
Tetapi anak itu tidak mau. Ia tidak mau melepaskan ibunya. Nampaknya anak itu sudah merasa sangat rindu kepada ibu dan ayahnya.
Di malam hari beberapa orang bebahu telah datang ke rumah Ki Demang demikian mereka mendengar Swandaru dan Pandan Wangi pulang. Mereka berbincang sampai jauh malam. Sebagian dari mereka bertanya tentang perjalanan Swandaru dan Pandan Wangi. Yang lain bertanya tentang keadaan Tanah Perdikan Menoreh.
Pandan Wangi tidak ikut menemui para bebahu. Tetapi dari ruang dalam serba sedikit ia dapat mendengarkan pembicaraan tentang rencana mereka mengajukan permohonan agar Kademangan Sangkal Putung ditetapkan menjadi tanah perdikan.
“Mungkin karena sejak awal Ki Demang tidak sependapat,” berkata Pandan Wangi di dalam hatinya.
Menjelang tengah malam, maka para bebahu itu pun minta diri. Ki Jagabaya yang juga sudah menjadi semakin tua pun berkata, “Besok aku akan datang pagi-pagi.”
“Baiklah, Ki Jagabaya,” sahut Swandaru.
“Sekarang, beristirahatlah.”
Sejenak kemudian, maka rumah Ki Demang itu pun menjadi sepi. Bahkan Ki Demang pun berkata kepada Swandaru, “Beristirahatlah. Kau dan istrimu tentu letih.”
“Ya, Ayah,” jawab Swandaru.
Ketika kemudian Swandaru masuk ke dalam biliknya, Pandan Wangi telah berbaring bersama anaknya yang sangat rindu kepada ibunya setelah ditinggal beberapa hari ke tanah perdikan.
Malam itu, Swandaru sempat merenungi pendapat Sekar Mirah tentang keinginan meningkatkan kedudukan Kademangan Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan.
Swandaru ternyata dapat mengerti pendapat Sekar Mirah, bahwa tanggapan Mataram akan dapat menjadi sebaliknya. Mereka tidak menyetujui permohonan untuk menetapkan Sangkal Putung menjadi tanah perdikan, tetapi bahkan sebaliknya. Mereka menganggap bahwa pengabdian Sangkal Putung selama ini justru mempunyai pamrih.
Swandaru yang memutuskan untuk membatalkan permohonannya itu justru merasa menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi merasa gelisah oleh keinginan yang berlebihan itu.
Beberapa saat kemudian, maka Swandaru pun telah terlena pula di samping anaknya yang juga sudah tertidur nyenyak. Pandan Wangilah yang justru masih belum tertidur. Tetapi beberapa saat kemudian. Pandan Wangi pun tertidur pula
Di pagi hari berikutnya, Swandaru justru nampak cerah. Hatinya terasa ringan tanpa beban. Ia tidak lagi mau memikirkan keinginan untuk menjadikan Kademangan Sangkal Putung itu menjadi tanah perdikan.
Ternyata pengaruh perjalanannya bukan saja membuatnya membatalkan niatnya tentang tanah perdikan, tetapi rasa-rasanya Swandaru benar-benar menjadi semakin dekat dengan Pandan Wangi, sehingga Swandaru itu seakan-akan sudah melupakan seorang perempuan cantik lainnya yang tersangkut di dalam kehidupannya.
Beberapa hari sejak Swandaru kembali dari Tanah Perdikan Menoreh ia tidak lagi ingat untuk pergi ke Kajoran menemui Wiyati. Bahkan ia pun telah lupa bahwa ia ingin memiliki kuda sebaik kuda Glagah Putih.
Jika Swandaru tidak berada di sawah, atau melihat anak-anak muda yang berlatih dalam olah kanuragan bersama para pengawal atau kepentingan-kepentingan lain di kademangannya, Swandaru berada di rumah bersama Pandan Wangi dan anaknya. Rasa-rasanya Swandaru tidak pernah merasa demikian dekat dengan keluarganya sebagaimana sejak ia pulang dari Tanah Perdikan Menoreh.
Namun ternyata sikap Swandaru itu sangat mencemaskan bagi Ki Ambara. Bagi Ki Ambara, Swandaru adalah alat yang sangat berarti untuk mencapai maksudnya. Di belakang Swandaru berdiri kekuatan yang besar yang akan dapat membantu Ki Ambara dan Ki Saba Lintang menghadapi Mataram. Apalagi jika Pandan Wangi berhasil membujuk ayahnya, Ki Gede Menoreh dan melibatkan kekuatan Tanah Perdikan Menoreh.
Karena itu, ketika Swandaru tidak kunjung datang ke Kajoran, maka Ki Ambara merasa sangat cemas.
“Apa yang sebaiknya aku lakukan, Ki Saba Lintang?” bertanya Ki Ambara.
“Apakah Swandaru masih belum kembali dari tanah perdikan?”
“Tentu sudah. Ia tidak akan dapat berlama-lama di tanah perdikan.”
“Apakah Ki Ambara akan mencoba pergi ke Sangkal Putung?”
“Aku masih belum tahu. apakah ada sesuatu yang akan mempengaruhinya.”
“Sebaiknya Ki Ambara pergi saja ke Sangkal Putung. Ki Ambara membawa kuda yang terbaik. Dibeli atau tidak dibeli. Dengan kehadiran Ki Ambara di Sangkal Putung, mungkin sekali akan dapat mengingatkan Swandaru kepada Wiyati.”
Ki Ambara mengangguk-angguk. Katanya, “Besok aku akan pergi ke Sangkal Putung. Tetapi Ki Saba Lintang harus bersiap-siap. Jika aku tidak pulang, Ki Saba Lintang harus mengambil aku di Sangkal Putung. Kekuatan yang segera dapat Ki Saba Lintang kumpulkan, serta sergapan yang tiba-tiba, akan dapat menyelamatkan aku. Selanjutnya, kita dapat melarikan diri meninggalkan Sangkal Putung dan Kajoran.”
Ki Saba Lintang mengangguk-angguk. Katanya, “Baiklah. Aku akan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Malam nanti aku akan mengirimkan isyarat kepada orang-orang kita yang terdekat.”
Ki Ambara mengangguk sambil berkata, “Baiklah. Hati-hati menghadapi Kademangan Sangkal Putung yang memiliki kekuatan yang besar. Meskipun tidak sebesar Tanah Perdikan Menoreh serta tidak memiliki orang-orang berilmu tinggi sebanyak Tanah Perdikan Menoreh. Asal Ki Saba Lintang bertindak cepat, maka pasukan Untara di Jati Anom tidak akan sempat membantu. Asal kita tidak mempertimbangkan untuk menduduki Sangkal Putung, sehingga gerakan itu hanyalah gerakan sekejap untuk mengambil aku dari kademangan itu, maka Ki Saba Lintang akan berhasil.”
“Baik. Aku mengerti.”
Malam itu, Ki Saba Lintang meninggalkan Kajoran untuk mencari hubungan dengan orang-orang yang berada di sarangnya yang terdekat. Diperintahkannya beberapa orang untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka secukupnya untuk satu gerakan mendadak seandainya Ki Ambara tidak keluar dari Sangkal Putung esok.
Di keesokan harinya, seperti yang direncanakannya, maka Ki Ambara pergi ke Sangkal Putung dengan naik kudanya yang terbaik. Ia menawarkan kudanya itu kepada Swandaru.
Kedatangan Ki Ambara di Sangkal Putung memang mengejutkan Swandaru. Ia pun mempersilakannya naik ke pendapa dan duduk di pringgitan.
Pandan Wangi yang kemudian mengetahui pula kehadiran Ki Ambara, telah menemui sejenak untuk mengucapkan selamat datang.
“Aku membawa kuda terbaik yang pernah aku miliki, Nyi,” berkata Ki Ambara
Pandan Wangi tertawa. Katanya, “Terserah saja kepada Kakang Swandaru.”
“Jika Nyi Pandan Wangi menghendaki, tentu Ki Swandaru akan membelikannya, berapa pun harganya.”
Pandan Wangi masih saja tertawa. Namun kemudian katanya, “Silakan Ki Ambara. Aku akan pergi ke dapur. Segala sesuatunya terserah kepada Kakang Swandaru.”
“Silakan, silakan Nyi.”
Ki Ambara mengangguk hormat Dalam pada itu, Ki Ambara memang tidak berbicara tentang hal-hal lain kecuali menawarkan seekor kuda yang sangat baik. Ia tidak mendahului berbicara tentang perempuan yang diakuinya sebagai cucunya, Wiyati.
Namun ternyata kedatangan Ki Ambara itu telah menyentuh jantung Swandaru. Swandarulah yang lebih dahulu bertanya, “Ki Ambara. Bagaimana keadaan Wiyati selama ini?”
“Cucuku itu baik-baik saja, Ngger. Jika ia kadang-kadang merenung dan sulit untuk dapat diajak berbicara itu dapat dimengerti.”
Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Meskipun tidak langsung, Ki Ambara memberitahukan kepadanya, bahwa Wiyati menunggu ke: datangannya.
“Tetapi jangan hiraukan. Perempuan seumurnya memang sering mengalami guncangan-guncangan perasaan seperti itu.”
Swandaru tidak menjawab. Tetapi nampak di wajahnya, bahwa hatinya telah tersentuh.
Namun ternyata Ki Ambara justru telah mengalihkan pembicaraannya. Ia kembali berbicara tentang kudanya yang dianggapnya terbaik yang pernah dimilikinya.
Tetapi dengan demikian, justru perasaan Swandaru menjadi semakin bergetar. Baginya, Ki Ambara nampak sebagai seorang tua yang rendah hati.
Ketika kemudian Pandan Wangi keluar lagi ke pringgitan sambil membawa nampan berisi minuman dan makanan, maka Ki Ambara pun berkata, “Sebenarnya tadi pagi aku sudah merasa ragu untuk datang kemari. Aku kira Ki Swandaru berdua masih berada di Tanah Perdikan Menoreh.”
“Kami sudah terlalu lama meninggalkan kademangan ini, Ki Ambara,” jawab Pandan Wangi, “Kakang Swandaru terikat oleh kewajiban-kewajibannya, justru karena ayah di sini sudah menjadi semakin tua.”
“Ya, ya, Ngger. Jika bukan Angger Swandaru lalu, siapa lagi yang akan membantu Ki Demang menjalankan tugas-tugasnya.”
“Itulah sebabnya, bahwa kami tidak dapat berada terlalu lama di tanah perdikan.”
Pandan Wangi masih ikut menemui Ki Ambara beberapa lama. Namun kemudian Pandan Wangi itu pun meninggalkan mereka kembali ke dapur.
Dalam pada itu, Ki Ambara tidak terlalu lama berada di Kademangan Sangkal Putung. Ia harus segera kembali dan memberi tahu Ki Saba Lintang, bahwa ia justru disambut dengan baik di Kademangan Sangkal Putung.
“Maaf Ki Ambara,” berkata Swandaru, “aku belum dapat memutuskan sekarang, apakah aku akan membeli kuda itu atau tidak.”
“Tidak apa-apa, Ngger,” sahut Ki Ambara dengan serta-merta, “aku juga hanya sekedar menawarkan. Selain itu, sudah agak lama kita tidak bertemu, sehingga aku memerlukan untuk datang berkunjung.”
“Terima kasih atas kunjungan ini, Ki Ambara.”
Ki Ambara pun kemudian telah minta diri pula kepada Pandan Wangi. Ketika ia keluar dari pintu regol halaman, Ki Ambara itu pun sempat berkata, “Nyi. Kami mengharap Nyi Pandan Wangi mengunjungi rumah kami. Bukankah sudah lama Nyi Pandan Wangi tidak melihat-lihat kandang kuda kami.”
Pandan Wangi tertawa. Katanya, “Kapan-kapan kami akan mengunjungi Ki Ambara. Yang menarik bukan kandang kuda Ki Ambara. Tetapi kesediaan Ki Ambara menerima kami.”
Ki Ambara pun tertawa.
Sejenak kemudian, maka Ki Ambara itu pun meninggalkan Kademangan Sangkal Putung. Di bulak-bulak yang sepi, maka kudanya berpacu dengan cepat. Ia harus segera bertemu dengan Ki Saba Lintang. Orang-orang yang telah dipersiapkan harus dikendurkan kembali. Semakin cepat semakin baik. Sebelum darah mereka mendidih oleh ketegangan yang mencekam.
Namun dalam pada itu, terjadi perubahan pada Swandaru sepeninggal Ki Ambara. Wajahnya tidak lagi nampak terlalu cerah.
Meskipun Swandaru berusaha untuk tetap nampak gembira, tetapi sentuhan gejolak jiwa terasa bergetar pula di dada Pandan Wangi.
Di sore hari, Swandaru duduk merenung di serambi gandok. Ia tidak menyadari bahwa Pandan Wangi mendekatinya sambil membawa minuman hangat. Karena itu, Swandaru terkejut ketika Pandan Wangi yang telah berdiri di sebelahnya itu berdesis, “Minumannya Kakang. Mumpung masih hangat.”
“Oh,” Swandaru menjadi gagap.
Pandan Wangi mengerutkan dahinya. Terasa sesuatu menyentuh perasaan halusnya sebagai seorang istri. Namun Pandan Wangi berusaha untuk meredamnya.
“Minum Kakang,” desis Pandan Wangi.
“Terima kasih,” Swandaru pun segera menggapai mangkuknya. Katanya, “Masih terlalu panas untuk diminum.”
Pandan Wangi tersenyum. Katanya, “Memang baru saja dituang, Kakang.”
Swandaru mencoba untuk tersenyum pula.
Pandan Wangi yang kemudian duduk di sebelah Swandaru pun kemudian berkata, “Jika kuda Ki Ambara itu menurut Kakang lebih baik dari kuda Kakang, sebaiknya Kakang membelinya saja.”
Swandaru mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, “Ki Ambara memberi harga terlalu tinggi, Pandan Wangi.”
“Kakang dapat tukar tambah dengan kuda Kakang yang lama. Bukankah kuda itu juga Kakang beli dari Ki Ambara?”
Swandaru mengangguk-angguk. Sekilas dipandanginya wajah Pandan Wangi yang bersih. Agaknya Pandan Wangi mengira, bahwa Swandaru masih saja merenungi kuda Ki Ambara yang memang nampak gagah dan tegar.
Dalam pada itu, Pandan Wangi pun berkata, “Bukankah Kakang juga tidak harus menurut saja harga yang ditawarkan oleh Ki Ambara? Kakang dapat saja menawar atas dasar penilaian Kakang sendiri.”
Swandaru mengangguk-angguk. Katanya, “Kapan kita pergi ke rumah Ki Ambara? Aku akan melihat kuda itu sekali lagi. Mungkin membawa dan mencoba untuk satu dua hari.”
Pandan Wangi tersenyum. Katanya, “Kakang dapat pergi sendiri. Jika Kakang menunggu aku, mungkin waktunya akan tertunda-tunda.”
Swandaru mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia pun berkata, “Besok aku akan pergi ke Kajoran.”
Pandan Wangi pun mengangguk-angguk. Dengan lembut ia pun berkata, “Pergilah, Kakang. Maaf aku tidak dapat ikut. Mungkin pada kesempatan lain.”
Sebenarnyalah di keesokan harinya, Swandaru pergi ke Kajoran. Sebenarnya Swandaru masih saja merasa ragu. Bahkan ia merasa malas waktu kudanya disiapkan di halaman.
Api di Bukit Menoreh
Jilid IV – 27
Bagian 3 dari 3
Namun akhirnya Swandaru itu pun pergi juga ke Kajoran.
Ketika Swandaru mendekati regol halaman rumah Ki Ambara, Swandaru merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Keragu-raguan telah mencengkam jantungnya. Ia sadar, sepenuhnya bahwa di rumah Ki Ambara itu terdapat seorang perempuan muda yang telah menjeratnya. Perempuan muda yang telah mempengaruhi jalan pikirannya dan bahkan pandangan hidupnya.
Ada semacam perlawanan di dalam dadanya terhadap niatnya datang menemui Ki Ambara. Pada hari-hari terakhir, ia merasa sangat dekat dengan istri dan anaknya. Swandaru ingin keadaan itu tidak terusik.
Tetapi di sisi lain, di sudut hatinya, ia merasa berkewajiban untuk, datang menemui perempuan yang bernama Wiyati itu.
Swandaru tidak dapat mengambil keputusan sampai kudanya berhenti di depan regol halaman rumah Ki Ambara.
Untuk beberapa saat lamanya, Swandaru masih duduk di punggung kudanya. Namun akhirnya ia pun meloncat turun. Seperti dihisap oleh kekuatan yang tidak dikenalnya, Swandaru akhirnya menuntun kudanya memasuki regol halaman rumah Ki Ambara.
Swandaru terkejut ketika ia mendengar suara seorang perempuan menjerit kecil menyebut namanya, “Kakang Swandaru!”
Swandaru berpaling. Ia melihat seorang perempuan muda yang berlari ke arahnya.
Jantung Swandaru tergetar. Perempuan itu adalah Wiyati.
Namun tiba-tiba saja Wiyati berhenti selangkah di hadapan Swandaru. Bahkan kepalanya pun menunduk sambil bergeser selangkah surut.
“Wiyati,” desis Swandaru.
“Maaf, Ki Swandaru. Aku tidak dapat menahan gejolak ke-gembiraanku melihat kedatangan Ki Swandaru.”
“Kenapa kau minta maaf?”
“Aku tidak yakin, apakah aku berhak melakukannya.”
“Sudahlah,” Swandarulah yang kemudian membimbing lengan Wiyati dan dibawanya naik ke pendapa.
“Ki Ambara ada?”
“Ada di dalam Ki Swandaru.”
“Aku akan menemuinya.”
“Baiklah. Aku akan menyampaikannya.”
“Tetapi selain Ki Ambara, aku juga ingin menemuimu.”
Wiyati memandang Swandaru sekilas. Namun wajahnya kembali menunduk. Ia sama sekali tidak menjawab.
“Sekarang sampaikan kepada Ki Ambara, bahwa aku ingin menemuinya. Tetapi kau pun harus ikut pula menemui aku nanti.”
“Baiklah, Ki Swandaru.”
Sesaat kemudian Wiyati pun telah masuk ke ruang dalam, sementara Swandaru duduk di pringgitan.
Beberapa saat kemudian, Ki Ambara pun telah keluar dari ruang dalam. Dengan ramah ia pun menyapa Swandaru yang sudah duduk lebih dahulu. Menanyakan keselamatan perjalanannya serta keluarga di Sangkal Putung.
Baru kemudian, Ki Ambara itu pun bertanya, “Apakah Nyi Pandan Wangi tidak sempat ikut datang kemari?”
“Pandan Wangi sedang sibuk, Ki Ambara. Mungkin lain kali.”
“Aku sangat mengharapkan kedatangannya.”
“Aku justru berharap agar Pandan Wangi tidak ikut bersamaku. Apalagi saat ini, setelah aku agak lama tidak berkunjung kemari.”
Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Swandaru bersikap jujur kepadanya.
Karena itu maka ia pun berkata, “Baiklah aku juga berterus terang Ki Swandaru. Selama ini Wiyati menjadi seperti orang bingung.”
“Wiyatilah sebenarnya yang mendorong aku pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Wiyati pula yang mendorong aku mempersoalkan kedudukan Kademangan Sangkal Putung untuk dapat ditetapkan menjadi tanah perdikan.”
Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Mimpi Wiyati memang ingin melihat Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan meskipun Wiyati hanya akan dapat melihat dari jarak yang jauh.”
Swandaru termangu-mangu, sementara Ki Ambara berkata selanjutnya, “Cucuku pun mengerti, apa yang sedang Angger Swandaru lakukan. Tetapi ketika Angger Swandaru pergi ke Perdikan untuk beberapa hari sehingga tidak dapat datang ke Kajoran, maka Wiyati nampak menjadi sangat kesepian.”
“Aku memang tidak dapat segera datang kemari tanpa alasan yang kuat, Ki Ambara,” berkata Swandaru.
“Aku mengerti. Wiyati pun mengerti pula. Karena itu, maka aku datang ke Sangkal Putung dengan seekor kuda yang tegar, meskipun aku merasa ragu, apakah aku akan diterima dengan baik. Mungkin telah terjadi perubahan pada Ki Swandaru setelah kembali dari Tanah Perdikan Menoreh.”
“Tidak ada perubahan apa-apa, Ki Ambara. Persoalannya hanya pada kesempatan saja.”
“Syukurlah,” Ki Ambara mengangguk-angguk.
“Nah, sekarang apakah Angger Swandaru akan berbicara dengan Wiyati?”
Swandaru mengangguk sambil menjawab, “Ya, Ki Ambara.”
“Aku akan memanggilnya.”
“Tidak usah, Ki Ambara. Aku sudah minta Wiyati duduk pula bersama kita di sini.”
Tetapi Ki Ambara justru bangkit sambil berkata, “Biarlah ia menemui Angger Swandaru. Mungkin ada yang ingin dikatakannya. Sebaiknya aku tidak mengganggunya. Nanti aku akan datang lagi ikut berbicara bersama kalian.”
Swandaru tidak dapat menahannya ketika Ki Ambara kemudian melangkah masuk ke ruang dalam untuk memanggil Wiyati.
Beberapa saat kemudian, Wiyati keluar dari ruang dalam sambil membawa minum dan makanan untuk disuguhkan kepada tamunya.
“Duduklah Wiyati,” berkata Swandaru.
Wiyati tidak membantah. Diletakkannya saja nampannya di sebelahnya, sementara Wiyati duduk sambil menundukkan kepalanya.
“Aku minta maaf Wiyati. bahwa agak lama aku tidak mengunjungimu.”
“Kenapa Ki Swandaru minta maaf kepadaku?”
“Kau tentu tahu maksudku. Sejak aku pergi ke tanah perdikan, baru sekarang aku dapat datang kemari. Aku memang sedang menunggu kesempatan. Untunglah bahwa Ki Ambara tanggap dan sempat datang ke Sangkal Putung, sehingga aku mempunyai alasan untuk datang kemari.”
“Kepergian kakek ke Sangkal Putung kemarin, tidak ada hubungannya dengan aku, Kakang.”
“Jangan begitu Wiyati. Aku datang untuk minta maaf.”
“Bukankah perjalanan ke Tanah Perdikan Menoreh itu merupakan perjalanan yang sangat menyenangkan? Tentu lebih menyenangkan daripada perjalanan pendek ke Kajoran.”
“Tetapi bukankah kau tahu bahwa aku pergi ke Tanah Perdikan Menoreh? Sebelum aku berangkat, aku berada di sini sampai jauh malam.”
“Apakah aku menyesali kepergian Kakang ke Tanah Perdikan Menoreh?” sahut Wiyati, “bukankah aku ikut bergembira, bahwa perjalanan Kakang berhasil untuk mendapatkan dukungan dari keluarga di Tanah Perdikan Menoreh agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan?”
Swandaru menarik nafas panjang. Sambil menggelengkan kepalanya Swandaru pun berkata, “Aku sudah melupakan gagasan untuk menjadikan Sangkal Putung sebuah tanah perdikan.”
“Kakang?” Wiyati terkejut, “Kenapa keinginan Kakang untuk meningkatkan kedudukan Kademangan Sangkal Putung begitu mudah patah?”
Swandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, “Aku sudah bertemu dengan saudara seperguruanku, Kakang Agung Sedayu. Aku berbicara panjang dengan Kakang Agung Sedayu dan istrinya, adikku Sekar Mirah. Akhirnya aku dapat mengerti pendapat mereka, bahwa sebaiknya aku mengurungkan niatku untuk mengajukan permohonan agar Sangkal Putung dapat ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan.”
“Sayang sekali,” desis Wiyati.
“Kenapa?”
“Aku ingin melihat Sangkal Putung dapat ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Setidak-tidaknya akan dapat ikut merasakan ke-banggaan yang sangat besar atas ketetapan itu.”
“Aku tidak dapat melakukannya, setidak-tidaknya untuk sementara, Wiyati. Apalagi Panembahan Senapati memang sedang sakit, sehingga perhatian semua orang di istana ditujukan kepada Panembahan Senapati.”
Wiyati yang cerdik itu tidak mempersoalkannya lagi. Ia masih mempunyai waktu. Ia yakin, bahwa setelah kunjungannya itu, Swandaru akan datang lagi dan datang lagi seperti sebelum pergi ke tanah perdikan.
Karena itu, yang kemudian dibicarakan oleh Wiyati tidak lagi menyangkut kemungkinan Sangkal Putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Tetapi Wiyati mulai berusaha untuk merampas kembali perhatian Swandaru. Sekali-sekali Wiyati itu tersenyum. Kemudian bersungut-sungut. Bahkan kemudian Wiyati itu mulai mencubit lengan Swandaru, sehingga akhirnya Swandaru tenggelam lagi dalam suasana yang lain dari kehidupannya di Sangkal Putung bersama anak dan istrinya.
Pada hari itu, Wiyati memang belum banyak berbicara tentang tanah Perdikan. Ketika kemudian Swandaru meninggalkan Kajoran, maka Ki Ambara pun bertanya kepadanya, “Bagaimana dengan niat Swandaru untuk mohon ketetapan agar Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan.”
Wiyati pun kemudian mengatakan tentang sikap Swandaru setelah ia pulang dari Tanah Perdikan Menoreh.
Wajah Ki Ambara menjadi tegang. Dengan kerut dahinya, ia pun bertanya, “Lalu apa yang kau katakan kepadanya?”
“Aku belum mengatakan apa-apa, Kek.”
“Kenapa kau tidak berusaha mendesak, agar Swandaru tetap pada keinginannya untuk mengajukan permohonan agar tanah perdikan Sangkal Putung itu dapat terwujud.”
“Jangan tergesa-gesa, Kek.”
“Maksudmu?”
“Jika aku mendesaknya sekarang, maka Swandaru akan mempertahankan sikapnya, tetapi jika aku membujuknya perlahan-lahan, mungkin aku akan dapat berhasil.”
“Tetapi kita tidak boleh terlambat.”
“Apa yang terlambat?”
“Mumpung Panembahan Senapati sedang sakit. Permohonan Swandaru tentu diabaikan. Bukankah kita ingin Swandaru tetap mengajukan permohonan itu tetapi ditolak.”
“Ya. Menurut pendapatku, apakah Panembahan Senapati masih sakit atau kemudian sudah sembuh, permohonan itu tentu akan ditolak. Tetapi aku mohon kakek jangan tergesa-gesa. Percayalah kepadaku.”
“Kalau Swandaru. itu tidak datang lagi kemari?”
Wiyati tersenyum. Katanya, “Ia akan datang lagi kemari. Yakinkan itu, Kek.”
Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Baiklah. Aku akan menunggu satu dua hari. Tetapi jika ia tidak datang, aku terpaksa pergi lagi ke Sangkal Putung menawarkan kuda itu lagi.”
“Percayalah.”
Ki Ambara tidak mendesak lagi.
Ternyata Wiyati benar. Ki Ambara yang ragu-ragu itu, kemudian harus meyakini kecerdikan Wiyati.
Seperti yang dikatakan oleh Wiyati, maka selang beberapa hari, Swandaru telah datang lagi ke Kajoran. Disusul dengan kedatangannya berikutnya. Semakin lama menjadi semakin sering.
Sebenarnyalah, Swandaru menjadi seperti terbius lagi. Wiyati baginya dapat memberikan suasana yang berbeda dengan suasana di rumahnya.
Pada saat-saat yang demikian itulah, maka Wiyati kembali berbisik di telinga Swandaru tentang tanah perdikan.
“Aku sudah memutuskan untuk membatalkan niatku,” berkata Swandaru.
Wiyati tersenyum. Ia pun kemudian bertanya, “Bagaimana dengan para bebahu? Apakah mereka juga begitu saja membatalkan niat mereka?”
“Mereka menurut saja apa yang aku katakan,” jawab Swandaru, “jika aku mengurungkan niatku, mereka pun sama sekali tidak berkeberatan.”
“Apakah Kakang Swandaru tidak merasa sayang, bahwa gelora di hati para bebahu itu harus diredam. Seperti api yang telah menyala bagaikan menjilat langit, harus dipadamkan begitu saja? Mereka memang patuh kepada Kakang. Tetapi api itu sebenarnya tidak pernah padam di dada mereka.”
“Mereka mengerti, Wiyati.”
“Kakang tidak boleh sedemikian mudahnya patah di tengah-tengah. Orang-orang Tanah Perdikan Menoreh tentu merasa cemburu jika Kademangan Sangkal Putung mendapat ketetapan menjadi tanah perdikan pula. Mereka akan merasa disaingi, sehingga karena itu, mereka menyusun alasan-alasan yang nampaknya masuk akal.”
“Memang masuk akal Wiyati,” sahut Swandaru.
Wiyati adalah seorang perempuan yang cerdik. Jika Swandaru nampak menjadi kesal, maka ia pun berhenti. Dialihkan pembicaraannya pada persoalan-persoalan lain yang lebih ringan. Namun yang dengan demikian, ia telah menjerat Swandaru semakin erat. Wiyati telah berbuat apa saja untuk dapat benar-benar merampas dan menguasai perasaan dan penalaran Swandaru, sehingga di hadapan Wiyati Swandaru pun seakan-akan telah berubah menjadi seorang yang semakin lama semakin kehilangan daya penalarannya.
Perlahan-lahan dengan penuh kesabaran, Wiyati masih saja menghembuskan gambaran tentang sebuah tanah perdikan yang memiliki kebebasan hampir mutlak.
“Kekuasaan sebenarnya seorang kepala tanah perdikan tidak ubahnya dengan kuasa raja sendiri,” berkata Wiyati.
“Tentu tidak, Wiyati,” berkata Swandaru, “mungkin untuk mengurus diri sendiri. Tetapi masih tetap dalam lingkungan bingkai kuasa seorang raja serta saluran-saluran kuasanya.”
“Kakang benar,” desis Wiyati. Tanpa menyebut tanah perdikan lagi, Wiyati menyandarkan kepalanya di dada Swandaru. Katanya, “Kakang, mataku mulai terpejam.”
“Kau mengantuk? Sedangkan udara panasnya seperti ini?”
“Panas sekali, Kakang. Aku tidak tahan mengenakan baju lurik yang tebal ini.”
Swandaru menarik nafas dalam-dalam.
Dalam pada itu, bagaimanapun juga Swandaru berusaha, namun Pandan Wangi merasakan bahwa telah terjadi perubahan pada suaminya. Kadang-kadang Swandaru itu merenung memandang ke kejauhan di serambi gandok. Namun kadang-kadang Swandaru itu justru bersikap sangat baik kepada Pandan Wangi.
Tetapi seperti sebelum mereka pergi ke Tanah Perdikan Menoreh, Swandaru menjadi sering pergi dengan alasan yang bermacam-macam. Bahkan kadang-kadang sampai jauh malam.
Ketika pada satu senja Pandan Wangi menemukan suaminya sedang merenung sendiri di pringgitan, maka Pandan Wangi itu pun duduk menemaninya
Semula Pandan Wangi memang merasa ragu untuk bertanya. Namun akhirnya Pandan Wangi itu memaksa dirinya untuk bertanya, “Kakang. Apakah sebenarnya yang Kakang renungkan. Setiap kali aku melihat Kakang duduk menyendiri sambil merenung. Mula-mula aku mengira bahwa Kakang tertarik kepada seekor kuda yang dibawa oleh Ki Ambara. Tetapi ternyata sampai saat ini Kakang tidak mengambil kuda itu. Namun nampaknya ada sesuatu yang Kakang renungkan.”
Swandaru memang menjadi agak sulit untuk menjawab. Tetapi kemudian ia pun berdesis, “Pandan Wangi. Aku mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada beberapa orang bebahu bahwa permohonan untuk menetapkan Sangkal Putung menjadi tanah perdikan ternyata tidak menguntungkan bagi kademangan ini sendiri.”
Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Jawaban Swandaru itu masuk di akalnya
“Kakang harus sabar,” berkata Pandan Wangi kemudian, “sedikit demi sedikit. Mereka sudah terlanjur terjebak terlalu jauh ke dalam mimpi. Karena itu agak sulit untuk mengangkat mereka kembali ke dalam kehidupannya yang nyata ini.”
“Aku sudah berusaha Pandan Wangi.”
“Seperti yang aku katakan, Kakang harus sabar.”
Swandarulah yang kemudian mengangguk-angguk. Katanya, “Aku juga berusaha sejauh dapat aku lakukan, Pandan Wangi. Aku sudah tidak menghitung waktu. Setiap kesempatan aku pergunakan. Kapan saja aku mendengar bahwa beberapa bebahu dan orang-orang kademangan ini yang berpengaruh berkumpul, aku selalu berusaha datang. Siang atau malam atau kapan saja.”
“Tetapi Kakang tidak usah memaksa diri. Kakang harus memperhatikan kesehatan Kakang sendiri.”
“Aku mengerti, Pandan Wangi. Aku memang ingin membatasi diri.”
Pandan Wangi duduk menemani suaminya beberapa lama. Namun ketika ia mendengar anak laki-lakinya memanggilnya, maka Pandan Wangi pun bangkit berdiri dan masuk ke ruang dalam.
Semula Pandan Wangi mengira bahwa Swandaru malam itu tidak akan pergi. Tetapi justru ketika malam turun, Swandaru itu pun telah menyiapkan kudanya
“Kakang akan pergi ke mana?” bertanya Pandan Wangi.
“Aku akan pergi ke Karangwetan sebentar Pandan Wangi.”
Pandan Wangi tidak mencegahnya. Dipandanginya saja Swandaru yang kemudian meloncat ke punggung kudanya.
Demikian Swandaru meninggalkan padukuhan induk, maka terasa jantungnya berdebaran. Ia sudah mulai membohongi Pandan Wangi lagi. Swandaru pun sadar, bahwa setiap kebohongan akan disusul oleh ke-bohongan yang lain. Namun Swandaru tidak mampu mencegahnya.
“Maafkan aku Pandan Wangi,” desis Swandaru.
Swandaru itu merasa dirinya seakan-akan telah terpecah. Kadang-kadang Swandaru itu bahkan merasa kehilangan diri sendiri. Ia merasa dirinya dicengkam oleh keinginan yang tidak terlawan, meskipun di sudut hatinya, tepercik kesadaran, bahwa ia telah mengambil langkah yang salah.
Jika saja Swandaru itu masih seorang kanak-kanak. Ingin rasanya untuk berteriak sekeras-kerasnya atau menangis sejadi-jadinya untuk mengosongkan beban di dadanya.
Tetapi kuda Swandaru berlari terus menuju ke Kajoran yang memang tidak terlalu jauh dari Sangkal Putung.
Demikian Swandaru tiba di Kajoran, maka ia pun segera tenggelam dalam pusaran yang mengaburkan segala macam penalarannya.
Sementara itu, setiap kali Wiyati masih saja berbisik tentang Tanah Perdikan Sangkal Putung.
Karena Swandaru nampaknya masih belum bergeser dari sikapnya tentang Tanah Perdikan Sangkal Putung, maka Wiyati mulai mengguncang perasaan Swandaru. Dalam keadaan yang larut oleh bius yang dihembuskan dari kehangatan sikap Wiyati, kadang-kadang Wiyati mulai menghindar.
“Wiyati,” suara Swandaru pun bergetar.
Seperti menghadapi anak-anak yang sedang kehausan, Wiyati berbicara tentang Tanah Perdikan Sangkal Putung.
Memang perlahan-lahan. Tetapi di dalam diri Swandaru itu telah tumbuh kembali keinginannya untuk menjadikan Sangkal Putung sebuah tanah perdikan.
“Kakang harus meyakinkan orang-orang Menoreh, bahwa Tanah Perdikan Sangkal Putung tidak akan menyaingi Tanah Perdikan Menoreh.”
Swandaru yang seakan-akan telah jatuh di bawah pengaruh Wiyati itu tidak dapat mengelak. Gagasan-gagasan Wiyati itu seakan-akan terpahat di jantungnya
“Wiyati benar. Orang-orang Tanah Perdikan Menoreh, bahkan Sekar Mirah, memang menjadi cemburu jika aku kelak menjadi seorang kepala tanah perdikan,” berkata Swandaru di dalam hatinya.
Di telinga Swandaru, Wiyati berkata, “Yakinkan mereka. Terlebih lagi Sekar Mirah, adik Kakang Swandaru itu. Bahkan ia pun akan terangkat pula namanya, jika Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan. Bukan sebaliknya, ia justru menjadi iri hati.”
Swandaru mengangguk-angguk. Mulutnya bagaikan terbungkam. Seperti anak-anak yang mendengar dongeng neneknya, Swandaru hanya mempunyai kesempatan untuk mendengarkan. Sekali-sekali bertanya. Kemudian mengangguk-angguk setelah mendengarkan satu dua kalimat jawaban.
Dalam pada itu, tiba-tiba saja rakyat Mataram benar-benar diguncang oleh berita, bahwa Panembahan Senapan benar-benar sakit. Bahkan sudah menjadi semakin parah, sehingga seisi istana menjadi cemas, bahwa tidak akan ada seorang tabib pun yang akan dapat mengobatinya.
Namun kemudian, para pejabat di istana masih tetap mengusahakan kesembuhan Panembahan Senapati.
Keadaan Panembahan Senapati itu tidak luput dari perhatian Ki Ambara. Kepada Wiyati Ki Ambara itu pun berkata, “Kita harus tanggap akan keadaan ini, Wiyati.”
“Ya, Kek.”
“Dorong Swandaru agar Swandaru segera mengajukan permohonan penetapan Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan.”
Wiyati mengangguk. Katanya, “Tidak sulit untuk memaksa Kakang Swandaru melakukannya. Tetapi agaknya ia masih saja terikat dengan Tanah Perdikan Menoreh.”
“Jika Swandaru kecewa, maka kita akan memanfaatkannya. Mudah-mudahan Pandan Wangi dapat mendukung kekecewaan suaminya dan membujuk ayahnya di tanah Perdikan.”
“Jika hal itu terjadi, apakah kita sendiri sudah siap, Kek?”
“Kita akan mempersiapkan diri. Ki Saba Lintang akan mempersiapkan pasukan yang besar, namun bergerak di bawah Tanah. Jika waktunya tiba, maka yang pertama-tama harus digilas adalah pasukan Untara di Jati Anom. Sementara itu, kita berharap bahwa Sekar Mirah akan dapat mempengaruhi suaminya, sehingga pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh akan berpihak kepada kekuatan yang dapat dihimpun oleh Tanah Perdikan Menoreh. Sebagian kekuatan kita akan berada di Tanah Perdikan Menoreh yang bersama-sama dengan kekuatan yang berada di Tanah Perdikan Menoreh, akan menyergap Mataram dari sisi barat, Kemudian pasukan dari Sangkal Putung setelah menghancurkan kekuatan Untara di Jati Anom akan menyerang Mataram dari arah timur. Kita akan memotong pasukan Mataram yang berada di Ganjur dan menghancurkannya sebelum memasuki Kota Raja.”
“Apakah kekuatan dari Pati, Demak, Jipang dan saudara-saudara kita di sebelah utara Gunung Kendeng dalam waktu dekat sudah akan berada di Sangkal Putung dan di Tanah Perdikan Menoreh?”
“Apakah kau yakin, bahwa Swandaru akan mengambil keputusan dalam waktu dekat? Jika permohonan itu diserahkan kepada Panembahan Senapati, bukankah diperlukan waktu untuk menunggu jawabannya? Baru atas dasar jawaban itulah Swandaru akan bergerak. Kita harus berpikir ulang jika permohonan itu justru dikabulkan oleh Panembahan Senapati yang sakitnya menjadi semakin keras.”
“Aku yakin, Panembahan Senapati atau para pejabat di Mataram yang menangani surat itu akan menjadi marah.”
“Kau pun harus yakin, bahwa kapan pun pasukan itu diperlukan, pasukan itu sudah akan berada di tempat masing-masing. Tetapi yang penting adalah sikap Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh lebih dahulu.”
Wiyati mengangguk-angguk. Katanya, “Baiklah. Aku akan mendorong Swandaru untuk segera mengajukan permohonan itu ke Mataram. Tetapi jangan sampai timbul salah paham dengan Tanah Perdikan Menoreh, karena kita memerlukan dukungan kekuatan di Tanah Perdikan Menoreh lewat Pandan Wangi.”
Sebenarnyalah, bahwa dalam waktu dekat, sikap Swandaru sudah berubah lagi. Tiba-tiba saja ia menjadi semakin mantap untuk menjadikan Sangkal Putung sebuah tanah perdikan.
Ki Demang Sangkal Putung dan Pandan Wangi masih berusaha mencegahnya. Namun Swandaru telah memberikan berbagai macam alasan untuk memperkuat sikapnya. Bahwa Sangkal Putung harus menjadi tanah perdikan.
“Selagi Panembahan Senapati masih ada,” berkata Swandaru, “Jika Panembahan Senapati itu wafat, maka penggantinya tidak akan dapat mengenali pengabdian yang telah diberikan Sangkal Putung kepada Mataram.”
“Kakang,” berkata Pandan Wangi, “bukankah Kakang sependapat dengan Sekar Mirah, bahwa pengabdian yang diberikan oleh Sangkal Putung itu tanpa pamrih.”
“Pada saat kami melakukannya, kami memang tidak mempunyai pamrih apapun. Tetapi jika dengan demikian Mataram menjadi semakin besar, apakah kita tidak dapat ikut menikmati kebesarannya? Bukan apa-apa. Hanya sekedar ketetapan bahwa Sangkal Putung akan menjadi sebuah Tanah Perdikan.”
Dengan nada dalam Ki Demang pun berkata, “Swandaru. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Jika Mataram menjadi besar, bukankah kita dapat ikut berbangga atas kebesarannya. Kesejahteraan Mataram akan tercermin juga di Kademangan Sangkal Putung ini. Tanpa menjadi tanah perdikan, Sangkal Putung sudah menjadi daerah yang kesejahteraannya selalu meningkat. Kau sendiri pernah mengatakan, bahwa kesejahteraan rakyat Sangkal Putung tidak kalah dengan kesejahteraan rakyat Tanah Perdikan Menoreh. Bukankah yang memberikan kepuasan bagi seorang pimpinan adalah jika rakyatnya hidup sejahtera dan bahagia?”
“Apakah itu cukup, Ayah? Bukankah kadang-kadang kita juga berpikir tentang harga diri? Tentang derajat dan pangkat? Bukan hanya semat?”
“Aku sependapat Swandaru. Tetapi kita juga harus merenungi cara kita mempertahankan harga diri, mendapatkan derajat dan pangkat. Bukankah kita tidak dapat membenarkan cara apapun tanpa menghiraukan nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan kehidupan kita sekarang?”
“Jika kita terlalu dibebani berbagai macam pertimbangan, keseganan dan keberatan, maka kita tidak akan dapat melakukan apapun juga.”
“Apakah kita akan dapat melepaskan diri dari beban itu? Apakah kita dapat berbuat apa saja tanpa dibebani pertimbangan, keseganan dan keberatan-keberatan berdasarkan nilai-nilai tatanan dalam lingkaran pergaulan luas ini?”
“Ayah,” berkata Swandaru kemudian, “adalah kewajiban kita untuk memperjuangkan masa depan kampung halaman kita. Agar kita tidak dikutuk oleh anak cucu kita, karena kita tidak berbuat apa-apa untuk meningkatkan kedudukan kampung halaman kita ini.”
“Meskipun demikian, aku minta kau mempertimbangkannya sekali lagi, Swandaru. Ketika kau pulang dari Tanah Perdikan Menoreh, kau membawa pertimbangan-pertimbangan yang cerah di dalam hatimu. Ketika kau meletakkan keinginanmu untuk mengajukan permohonan agar kademangan ini ditetapkan menjadi tanah perdikan, kau nampak menjadi ceria, justru kau telah meletakkan beban yang memberati perasaanmu.”
“Ternyata itu justru satu kemunduran, Ayah. Aku memang seorang yang lemah. Yang mudah patah menghadapi tantangan-tantangan. Namun ketika hal itu aku sadari, maka hatiku menjadi kukuh kembali. Aku akan tetap mengajukan permohonan atas nama rakyat Kademangan Sangkal Putung, agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi tanah perdikan.”
“Swandaru. Kenapa tidak kau sukuri saja karunia yang melimpah bagi kita semuanya di kademangan ini? Jika kau sempat mengingat masa kecilmu, tanah ini tidak banyak memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun karena kita sudah menunjukkan usaha yang bersungguh-sungguh dengan kerja keras, maka sebagaimana kita lihat sekarang, pada kademangan ini telah dikaruniakan-Nya kesejahteraan yang semakin tinggi.”
“Bukankah dengan demikian karunia itu tidak datang dengan sendirinya, Ayah? Bukankah kita harus bekerja keras sebagai lantaran turunnya karunia itu? Nah, kita sekarang tidak boleh berhenti berusaha. Setelah itu mensyukuri karunia ini, maka kita wajib berusaha untuk meningkatkan tanah yang dipercayakan kepada kita ini agar kedudukannya semakin meningkat.”
“Kakang,” berkata Pandan Wangi kemudian, “tetapi bagaimanapun juga kita harus mengingat keadaan Panembahan Senapati sekarang. Jika Kakang mencemaskan kelangsungan kuasa Panembahan Senapati sehingga penggantinya tidak akan mengetahui dan tidak akan mampu menilai pengabdian yang telah Kakang berikan, apakah dalam keadaan sakit yang parah Panembahan Senapati akan dapat melakukannya?”
“Bukankah ada orang lain yang dapat menyampaikan pertimbangan-pertimbangan bagi Panembahan Senapati? Orang-orang yang pengenalannya atas kademangan ini sama dengan Panembahan Senapati, sehingga Panembahan Senapati tinggal mengiakannya? Jika yang berkuasa kemudian adalah penggantinya yang masih muda itu, maka kuasanya itu dapat mencegah orang-orang yang sebenarnya menyetujui permohonan kami.”
Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Ki Demang pun merasa bahwa sulit baginya untuk mencegah niat Swandaru yang bagi Ki Demang, kurang pada tempatnya itu.
Dalam pada itu, Swandaru pun bahkan berkata, “Pandan Wangi Aku akan mengirimkan utusan ke Tanah Perdikan Menoreh. Aku akan memberitahukan bahwa aku telah mengirimkan surat permohonan kepada Kangjeng Panembahan Senapati. Aku akan minta agar Kakang Agung Sedayu dan Ki Gede Menoreh mendukung permohonanku. Jika mereka sempat bertemu dengan para pembesar di Mataram, terutama Kakang Agung Sedayu, akan mengharap agar Kakang Agung Sedayu membantu mempengaruhi pendapat mereka.”
“Bukankah Kakang Agung Sedayu sudah menyatakan pendapatnya sejalan dengan pendapat Sekar Mirah?” jawab Pandan Wangi.
“Tetapi jika permohonan itu sudah aku sampaikan, maka aku berharap mereka akan bersikap lain.”
“Kakang,” desis Pandan Wangi, “aku mohon Kakang mempertimbangkannya sekali lagi.”
Tetapi Swandaru menggelengkan kepalanya. Katanya, “Aku sudah memikirkan masak-masak, Pandan Wangi.”
Pandan Wangi hanya dapat memandang Ki Demang dengan wajah yang gelisah. Apalagi ketika kemudian Swandaru itu pun berkata, “Pandan Wangi. Aku akan minta bantuanmu.”
“Bantuan apa Kakang?”
“Sudah aku katakan, bahwa aku akan mengirimkan utusan ke Tanah Perdikan Menoreh untuk memberitahukan, bahwa aku sudah mengajukan surat permohonan kepada Kangjeng Panembahan Senapati untuk menetapkan Kademangan Sangkal Putung sebagai Tanah Perdikan Sangkal Putung, dengan keterangan, apa saja yang pernah kita lakukan untuk mendukung kebesaran Mataram. Aku akan minta Ki Gede Menoreh untuk mendukung permohonan kami itu. Terutama Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu. Jika perlu aku minta Kakang Agung Sedayu datang menghadap Ki Patih Mandaraka, agar Ki Patih bersedia mempengaruhi Kangjeng Panembahan Senapati.”
“Kakang, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi. Kita tentu tidak akan dapat mengharap bahwa Kakang Agung Sedayu menemui Ki Patih. Kemudian minta agar Ki Patih menghadap Kangjeng Panembahan Senapati yang sedang sakit.”
“Apakah keberatan mereka? Bukankah Kakang Agung Sedayu sering pergi ke Mataram? Dan bukankah Ki Patih Mandaraka juga menghadap Kangjeng Panembahan Senapati setiap hari.”
“Kita tidak dapat seakan-akan memerintah mereka untuk kepentingan kita.”
“Aku tidak memerintah mereka. Tetapi apa keberatan mereka jika mereka melakukannya?”
“Jika Ki Patih Mandaraka justru tidak setuju dengan permohonan Kakang.”
“Ki Patih tahu benar pengabdian yang telah kita berikan bagi Mataram. Ki Patih tentu akan setuju. Ia pun akan bersedia untuk mempengaruhi Kangjeng Panembahan Senapati.”
Pandan Wangi menjadi bingung. Dipandanginya suaminya dengan tajamnya. Ia ingin melihat, bayangan apakah yang ada di mata suaminya, sehingga penalarannya seakan-akan tidak berjalan wajar.
Tetapi Pandan Wangi tidak dapat melihat, bahwa di kepala Swandaru itu bertengger seorang perempuan muda yang cantik dan cerdik, Wiyati.
“Pandan Wangi,” berkata Swandaru, “Aku perlu bantuanmu, agar kau bersedia pergi ke tanah perdikan. Kita akan berangkat bersama-sama. Aku pergi ke Mataram dan kau langsung pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Mungkin aku akan mendapat jawaban segera. Tetapi mungkin aku harus menunggu. Bahkan mungkin aku harus kembali lebih dahulu ke Sangkal Putung sebelum aku mendapatkan jawabnya karena Mataram memerlukan waktu untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam hal yang demikian itulah, aku berharap agar Kakang Agung Sedayu segera saja pergi menemui Ki Patih Mandaraka. Kakang Agung Sedayu pun harus minta pula agar Ki Patih segera menyampaikan pertimbangannya kepada Panembahan Senapati.”
“Swandaru,” berkata Ki Demang, “bagaimana mungkin kau dapat berkata bahwa Ki Lurah Agung Sedayu harus segera pergi menemui Ki Patih, kemudian Ki Patih harus segera menghadap Kangjeng Panembahan Senapati. Apakah hakmu mengharuskan mereka segera melaksanakan keinginanmu.”
“Ayah, sudah aku katakan, apakah keberatan mereka? Sedangkan persoalan ini sangat penting bagi kami, rakyat Sangkal Putung. Mereka harus mengerti, bahwa mereka melakukannya bagi rakyat sekademangan Sangkal Putung.”
“Ki Patih Mandaraka tidak hanya mempunyai kewajiban memenuhi keinginanmu atas nama rakyat Sangkal Putung. Tetapi Ki Patih Mandaraka memikirkan kepentingan rakyat seluruh Mataram. Memikirkan rakyat di satu wilayah yang luas sekali, beratus kali lipat dari Sangkal Putung.”
Swandaru mengerutkan dahinya. Sejenak ia merenungi kata-kata ayahnya. Sementara itu ayahnya pun berkata, “Kau tidak dapat memandang Mataram dari sudut kepentinganmu, seolah-olah kau adalah pusat perputaran dunia Mataram, sehingga semua orang harus memperhatikanmu, melakukan keinginanmu tanpa menghiraukan kepentingan-kepentingan lain yang jauh lebih besar dari sekedar kepentingan rakyat Sangkal Putung.”
Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Agaknya jantungnya dapat disentuh oleh kata-kata ayahnya itu. Meskipun demikian, ia pun masih berkata, “Baiklah Ayah. Aku juga menghormati kepentingan-kepentingan lain itu. Namun aku minta Kakang Agung Sedayu memperhatikan pula permintaanku dan memenuhinya demikian ada kesempatan. Demikian pula agar Kakang Agung Sedayu memohon kepada Ki Patih Mandaraka, untuk memperhatikan permohonan kami.”
Pernyataan Swandaru yang lebih lunak itu sedikit melegakan perasaan Ki Demang dan Pandan Wangi. Mereka masih berharap bahwa nalar Swandaru menjadi semakin berkembang dan melihat kenyataan yang terjadi di Mataram.
Tetapi agaknya Swandaru tidak akan bergeser lebih mundur lagi. Ia sudah berketetapan hati untuk pergi ke Mataram bersama-sama dengan ke-berangkatan Pandan Wangi ke Tanah Perdikan Menoreh untuk menghadap ayahnya dan menemui Agung Sedayu dan Sekar Mirah.
Di hari berikutnya, Swandaru pun telah menyiapkan surat yang akan diserahkan kepada Kangjeng Panembahan Senapati di Mataram. Kepada Ki Demang dan Pandan Wangi, Swandaru berkata, bahwa ia akan menunjukkan surat itu kepada para bebahu lebih dahulu. Apakah surat itu sudah pantas atau belum.
Namun sebenarnyalah bahwa Swandaru telah pergi ke Kajoran. Wiyatilah yang menyusun surat yang akan dibawa ke Mataram itu atas dasar pikiran dan gagasan Ki Ambara dan Ki Saba Lintang. Meskipun Swandarulah yang menulisnya. Surat itulah yang kemudian ditunjukkan kepada Ki Demang dan kepada Pandan Wangi.
“Surat itu aku buat berdasarkan pikiran, gagasan dan pertimbangan beberapa orang bebahu, sehingga isinya benar-benar mewakili pikiran, gagasan dan pendapat rakyat kademangan ini.”
Ki Demang hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Surat itu memang ditulis dengan susunan kalimat yang rapi dan manis. Namun isinya tetap saja kurang mapan menurut pendapat Ki Demang dan Pandan Wangi.
Tetapi Swandaru itu pun berkata, “Besok kita berangkat. Aku akan pergi ke Mataram bersama dua orang bebahu. Kau akan langsung pergi ke tanah perdikan bersama dua orang pengawal pilihan yang tidak akan mengecewakan bila kau menjumpai hambatan di perjalanan.”
Pandan Wangi tidak menolak. Ia memang merasa bahwa ia adalah orang terbaik untuk pergi ke Tanah Perdikan Menoreh dengan tugas yang hampir tidak masuk di akalnya itu.
“Tidak ada orang lain yang pantas melakukannya,” berkata Pandan Wangi kepada Ki Demang ketika mereka berbicara berdua.
“Kenapa?” bertanya Ki Demang.
“Akulah orang Sangkal Putung yang paling mengenal Ki Gede Menoreh, Sekar Mirah serta Kakang Agung Sedayu selain Kakang Swandaru sendiri.”
“Tetapi agaknya penalaran Swandaru baru kabur.”
“Tidak ada seorang pun yang dapat mengurungkan maksudnya. Ketika kami pulang dari tanah perdikan beberapa waktu yang lalu, aku merasa bahwa sepercik cahaya berhasil menerangi batinnya. Pendapat Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu dapat dimengertinya. Namun, tiba-tiba keinginannya itu tumbuh kembali.”
“Kau curiga bahwa ada seseorang yang mempengaruhinya?”
Pandan Wangi menundukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan Ki Demang sendirilah yang menjawab, “Mungkin di antara para bebahu. Besok, setelah kalian berangkat, aku akan berbicara dengan para bebahu.”
Pandan Wangi mengangguk sambil menjawab, “Mudah-mudahan Ayah mendapatkan beberapa petunjuk meskipun sudah agak terlambat. Namun bukan berarti bahwa keterangan yang Ayah dapatkan itu tidak ada gunanya.”
Ki Demang mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, “Beristirahatlah. Besok kau akan menempuh perjalanan panjang,”
“Aku akan menunggu Kakang Swandaru.”
“Tidak usah, Pandan Wangi. Suamimu agaknya tidak akan segera pulang.”
Tetapi sambil tersenyum Pandan Wangi pun berkata, “Aku tentu tidak akan dapat tidur, Ayah.”
Sebenarnyalah bahwa Pandan Wangi tidak segera pergi ke biliknya. Meskipun malam sudah menjadi semakin larut, serta Ki Demang dan seisi rumah itu sudah tidur nyenyak. Lewat tengah malam, Swandaru baru pulang. Ketika ia melihat Pandan Wangi membuka pintu dengan matanya yang masih bening, ia pun bertanya, “Kau belum tidur, Pandan Wangi?”
“Belum Kakang.”
“Seharusnya kau beristirahat karena besok kau akan menempuh perjalanan jauh.”
“Aku tidak dapat tidur mendengkur di dalam bilikku yang hangat, sementara Kakang Swandaru sibuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kepergian Kakang esok. Kakang Swandaru masih hilir mudik di udara malam yang dingin sepanjang jalan kademangan dalam tugas Kakang bagi kademangan ini.”
Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Terasa jantungnya tersengat oleh kesetiaan istrinya, sementara ia baru saja pulang dari rumah seorang perempuan muda di Kajoran. Wiyati memang lebih muda dari Pandan Wangi. Lebih segar, sedikit manja. Tetapi apakah bobot kesetiaan Wiyati dapat menyamai bobot kesetiaan Pandan Wangi? Bahkan Wiyati dapat menerimanya selagi ia masih terikat dalam perkawinan dengan seorang perempuan, itu sudah merupakan cacat bagi Wiyati.
Swandaru melangkah sambil menundukkan kepalanya, sementara Pandan Wangi menutup pintu butulan dan menyelarakkan kembali.
Dengan lesu Swandaru pun duduk di ruang dalam. Sesaat ia tidak dapat berkata apa-apa.
“Kau kenapa Kakang?”
Swandaru mengangkat wajahnya. Dahinya pun berkerut. Baru kemudian ia pun menjawab, “Aku tidak apa-apa, Pandan Wangi.”
“Kakang nampak gelisah.”
“Ya,” Swandaru termangu-mangu sejenak. Disadarinya bahwa untuk menutupi sebuah kebohongan, ia harus berbohong pula, “para bebahu sudah tidak sabar lagi.”
Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah, ia pun berkata, “Kakang jangan terlampau menuruti keinginan mereka, tanpa mengukur kekuatan dan ketahanan tubuh Kakang. Jika Kakang menjadi terlampau letih dan bahkan sakit, maka segala-galanya justru akan tertunda.”
Swandaru termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia pun berkata, “Aku tidak dapat mengingkari kewajibanku.”
“Kewajiban yang mana yang Kakang ingkari? Kakang besok akan pergi ke Mataram. Jika Kakang besok berangkat, bukankah Kakang tidak ingkar akan kewajiban Kakang? Haruskah Kakang berbincang sampai jauh malam? Apakah itu juga menjadi bagian tugas Kakang yang harus Kakang lakukan sebelum Kakang berangkat ke Mataram esok pagi?”
Swandaru termangu-mangu. Tetapi ia tidak menjawab.
Pandan Wangi tidak mendesaknya. Ia pun kemudian berkata, “Nah, sekarang, Kakang harus beristirahat. Bukan hanya aku yang harus beristirahat.”
Swandaru mengangguk.
Demikianlah, maka keduanya pun telah masuk ke dalam bilik mereka. Tetapi keduanya tidak segera dapat memejamkan mata mereka meskipun mereka saling berdiam diri.
Baru di dini hari keduanya sempat memejamkan mata mereka Tetapi hanya sebentar, karena beberapa saat kemudian, maka mereda harus sudah bangun lagi.
Ketika langit menjadi cerah, menjelang matahari terbit, maka dua orang bebahu yang akan pergi bersama Swandaru ke Mataram serta dua orang pengawal terpilih yang akan mengawal Pandan Wangi ke Tanah Perdikan Menoreh telah bersiap.
Swandaru, Pandan Wangi dan mereka yang akan menyertai mereka pergi, segera minta diri kepada Ki Demang di Sangkal Putung yang sudah menjadi semakin tua.
“Hati-hatilah. Tidak hanya di sepanjang jalan. Tetapi juga di Mataram dan di Tanah Perdikan Menoreh. Kalian tidak hanya sekedar berkunjung. Tetapi kalian mengemban tugas kalian masing-masing.”
“Ya, Ayah,” jawab, Swandaru sambil mengangguk dalam-dalam.
Pandan Wangi pun Kemudian mencium tangan ayah mertuanya sambil berdesis, “Doa restu ayah yang aku mohon.”
“Aku akan selalu berdoa untukmu, Pandan Wangi. Kau adalah seorang perempuan panutan di Sangkal Putung.”
“Pujian itu terlalu tinggi bagiku, Ayah.”
“Menurut pendapatku, sebutan itu tepat bagimu.”
“Terima kasih, Ayah.”
Swandaru yang mendengar pujian ayahnya terhadap Pandan Wangi menjadi berdebar-debar. Perasaan bersalah yang tersimpan di dalam dadanya, serasa telah terungkit.
“Apakah Ayah sengaja menyindir aku? Apakah Ayah tahu, bahwa di samping Pandan Wangi masih ada perempuan lain di dalam hidupku?”
Terasa wajah Swandaru menjadi panas. Karena itu, maka ia pun kemudian berdesis, “Marilah kita berangkat, Pandan Wangi.”
Demikianlah, sejenak kemudian, Swandaru, Pandan Wangi dan para pengiringnya telah meninggalkan Kademangan Sangkal Putung. Mereka melarikan kuda mereka tidak terlalu kencang.
Hari masih pagi. Matahari baru saja terbit di ujung timur. Di wajah langit yang bersih, selembar awan yang tipis mengalir perlahan ke utara.
Swandaru dan Pandan Wangi menyusuri jalan di antara kotak-kotak sawah yang terbentang luas dari cakrawala sampai ke cakrawala, diselingi oleh padukuhan-padukuhan yang berpencar seperti pulau-pulau kecil yang tersembul di permukaan laut yang tenang. Namun jauh di kaki gunung, nampak hutan yang lebat membujur panjang.
Tidak banyak yang mereka bicarakan di sepanjang jalan. Swandaru masih memberikan pesan-pesan kepada Pandan Wangi, apakah yang harus dikatakan dan dilakukan di Tanah Perdikan Menoreh.
“Kita tidak boleh dipengaruhi lagi oleh jalan pikiran Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu. Mungkin kita memang berbeda sikap. Tetapi Sangkal Putung telah mengambil keputusan.”
“Baik, Kakang,” jawab Pandan Wangi. Ia tidak mempunyai pilihan lain dari jawaban itu.
“Tetapi aku tidak boleh bersikap kasar terhadap Ki Gede, terhadap Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu. Kau harus dengan sabar meyakinkan mereka seandainya mereka tetap pada pikiran-pikiran mereka yang terdahulu. Bagaimanapun juga kita perlu dukungan dari Ki Gede terutama Kakang Agung Sedayu yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Mataram. Syukurlah jika Kakang Agung Sedayu sendiri sempat langsung berbicara dengan Kangjeng Panembahan Senapati yang sedang sakit itu.”
*****
Horeeee ngrapel
Absen kiye… 😀
Saya tertarik cerita Api di Bukit Menoreh
Kalau ingin memperoleh buku2 dimaksud, ke mana harus membeli